Sejak berdirinya UGM, telah begitu banyak “kasak-kusuk” yang harus dilalui universitas besar tersebut. Pada masa-masa revolusi, terutama pada 1950-1965, UGM hadir dalam persilangan politik dan ideologi kanan, kiri, tengah, dan berbagai pencarian politik dan ekonomi untuk mengisi dan “memapankan” Indonesia merdeka.
Terdapat lima situasi dan kondisi yang secara relatif UGM berhasil melewatinya. Pertama, struktur dan konstruksi oposisional cukup jelas sehingga UGM tidak ragu harus berafiliasi ke siapa dan ke mana.
Kedua, semangat “baru saja merdeka” menyebabkan kampus lebih solid dan kompak dalam mengisi dan membangun Indonesia yang harus lebih mandiri.
Ketiga, mekanisme dan kemampuan teknologi komunikasi yang “tidak lebar ke mana-mana” menyebabkan kampus lebih fokus dalam berkiprah dan mengembangkan tangung jawab akademiknya.
Keempat, fasilitasi sosial dan politik yang tidak banyak menyebabkan ruang-ruang aksi terkondisi secara terbatas di satu sisi, tetapi menyebabkan keakraban warga kampus lebih terjaga.
Kelima, jarak kelas ekonomi warga kampus belum menyolok (Yang jelas, mahasiswa bawa mobil BMW kayaknya belum ada). Ekonomi negara juga masih kerja keras untuk membangun. Tapi, inflasi terus membesar. Masyarakat kelas menengah relatif belum muncul, alias masyarakat Indonesia sebagian besar miskin. Hanya untuk mendengar Soekarno pidato, sejumlah orang perlu berkumpul untuk mendengar dari satu radio.
Setelah tahun 1965, kondisi dan ujian buat UGM memasuki fase berikutnya. Soeharto segera memperkuat barisan kekuasannnya. Tahun 1974 dan 1978 ada demonstrasi besar di beberapa kampus Indonesia, termasuk di UGM. UGM selamat karena hampir semua kampus di Indonesia juga kompak dalam bersikap.
Negara masih memberi angin bahwa gerakan mahasiswa dianggap relatif murni. Bahkan saya ingat, pemimpin kampus UGM sebagian ikut demonstrasi. Martabat mahasiswa naik, bahwa mahasiswa adalah perpanjangan suara rakyat dan mahasiswa adalah rakyat itu sendiri. Terlepas dari beberapa mahasiswa yang beda haluan politiknya, yang jelas nama mahasiswa hingga tahun-tahun itu lumayan wangi dan harum.
Karena itu pula, mahasiswa menjadi lebih percaya diri. Pada masa-masa itu, mahasiswa banyak mengambil insiatif-inisiatif sosial dan ekonomi dan mulai berorganisasi atau bergabung dengan ormas dan orsospol. Sebagian berafilisiasi secara politik, sebagian relatif independen.
Kita tahu, kekuasaan Soeharto semakin mengetatkan kekuasaannya. Bersama Golkar, militer dirangkul erat, dan Islam dijinakkan sebagai tameng. Kekuasaan Soeharto berkembang menjadi otoritarian. Orang kaya baru karena KKN mulai bermunculan. Kelas menengah mulai hadir di banyak kota besar.
Sepanjang rentang setelah 1977 hingga sepanjang 1980-an, banyak pejabat; dari menteri, dirjen, hingga bupati/wali kota diisi oleh alumni UGM yang sudah mulai tersebar sejak 1960-an. Tentu jabatan penting dan strategis lainnya masih didominasi militer (waktu itu termasuk kepolisian).
UGM masih menjadi salah satu universitas paling penting untuk kuliah di situ. Hal itu terkondisi karena beberapa universitas di luar Jawa sedang menata diri. Boleh dikata, masa itu mahasiswa UGM merupakan kumpulan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kelak, setelah tahun 2000-an, UGM bukan lagi pilihan utama, karena sejumlah universitas di kota-kota Indonesia semakin baik dan mapan.
Namun, sepanjang dekade 1980-an dan 1990an, mahasiswa mulai banyak merasakan tekanan dan kontrol. Pembangunan berjalan semu karena wacana tentang kepemimpinan Soeharto diatur ketat. Siapa yang main-main digebug. Suara-suara kegelisahan dan aksi tampil kecil-kecil dan terbatas, bahkan sebagian hanya bisa bersuara di ruang-ruang diskusi, tentu sambil sembunyi-sembunyi. Itu pun sebagian besar di luar di kampus. LSM berkembang biak.
Di ujung dekade 1980-an, mahasiswa mulai demonstrasi. Memasuki tahun 1990-an, suasana mulai berubah. Perkembangan teknologi komunikasi dengan cepat menghubungkan mahasiswa se-Indonesia. Rakyat mendukung mahasiswa karena nama dan citra mahasiswa masih bagus. Musuh mahasiswa UGM juga jelas: kekuasaan Soeharto.
Mahasiswa kompak, tidak/belum direcoki afiliasi politik. Walau sudah ada mahasiwa anak orang kaya di UGM, mahasiswa kaya tersebut tahu diri untuk tidak tampil beda. Di Yogya, Ngarso Dalem dan Pemimpin Kampus langsung turun ke lapangan. Akhirnya. demonstrasi ada hasilnya. UGM memasuk ruang baru, sekaligus ujian baru berikutnya.
Memasuki dekade 2000-an, suatu masa demokratisasi dan reformasi, semua orang Indonesia berbenah diri. Dampak demokratisasi, sepak terjang berbagai afilisasi politik semakin deras masuk kampus. Politik kehilangan arah perlawanan. Belajar dari pengalaman alumni UGM yang “sukses”, kalau mau jadi orang atau pejabat penting, perlu dimulai untuk “mencuri perhatian di kampus”.
Banyak aktivis kampus, sebagian terkoneksi dengan kelompok atau partai politik tertentu. Partai politik meledak banyak sampai saya tidak tahu berapa jumlahnya (Bisa sih dicek kalau mau).
Sepanjang kekuasaan SBY, 2004-2009-2014 adalah masa-masa yang seolah “baik-baik saja”, tapi kampus UGM mengalami pamatangan yang membara. Nama besar UGM menjadi rebutan banyak kepentingan politik karena terdapat sejumlah alumni yang muncul sebagai kekuatan politik baru. Tokoh-tokoh alumni UGM yang muncul ke puncak nasional antara lain Jokowi, Anies, Ginanjar, Imin, Airlangga, Mahfud MD, dan sebagainya. UGM juga menghadirkan sejumlah pemikir politik yang unggul.
Hal itu memuncak ketika Jokowi, pada 2014, naik jadi presiden. Maka, UGM mulai retak antara yang merasa mendukung Jokowi dan yang merasa mendukung yang lain. Tapi, yang jelas UGM kecipratan keren, ada alumninya yang jadi presiden. Keretakan internal UGM semakin mencolok hingga 2019, dan lebih-lebih pada 2024.
Dalam keretakan, internal UGM mengalami rasa sangat sungkan dan saling hati-hati. Kita tidak tahu, siapa terkoneksi dengan siapa. Siapa masuk ke jaringan politik siapa dan yang mana. UGM mengalami rasa kaku dan sekaligus tidak nyaman.
Mahasiswa juga terkotak-kotak dan terafilisasi ke berbagai jaringan politik. Yang cuek politik juga banyak dan tetap kuliah/belajar sebagai mana mestinya. Diskusi-diskusi politik terpecah. Ada yang masih berusaha akademik dan secara terbatas di akomodasi oleh kampus.
Yang tidak berpretensi akademik, diskusi politiknya biasanya di luar kampus dan itu pun sangat hati-hati karena takut ketahuan afiliasi politiknya. Media sosial ikut mengacaukan citra dan nama baik mahasiswa. Situasi itu menyebabkan UGM seperti bertahan sebagai samsak.
Dulu, UGM jelas siapa yang harus dihadapi. Sekarang, UGM menghadapi satu situasi bahwa yang dihadapi sebagian besar adalah alumninya sendiri, yang terlanjur besar dan ada di mana-mana. Beberapa tahun lalu, pimpinan mahasiswa UGM mengelurkan pernyataan bahwa Jokowi merupakan alumni yang memalukan.
Belum lama ini, BEM UGM mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya pada pimpinan UGM, jika UGM tidak memperlihatkan keberpihaknnya kepada masyarakat sipil dan rakyat dan meminta UGM mengambil sikap yang tegas.
Banyak urusan internal yang menguras energi. Urusan kekerasan seksual, efisiensi yang membuat universitas seperti universitas kere, kasus-kasus insidental dan aksidental yang tetap meminta perhatian. Salah satu yang viral tentu bagaimana sekelompok kecil alumni UGM menggugat keaslian ijazah mantan presiden dari UGM.
Teman-teman senior di UGM sungkan harus ngapain dan berbuat apa, karena, lagi-lagi, adanya rasa ewuh-pakewuh. Sebagian berpendapat, “Nanti akan lewat dan teratasi satu-satu dengan sendirinya. Serahkan pada waktu. Waktu yang akan menyelesaikannya.” Ah, baiklah.
Saya belum tahu, ke mana Presiden Prabowo membawa Indonesia. Dari berbagai kebijakan Presiden selama lebih kurang 7 bulan ini, Prabowo tidak menempatkan universitas sebagai ruang-ruang riset dan pemikiran yang penting. Kesan saya, mungkin salah, Prabowo tidak membutuhkan intelektual dan akademisi organik, apalagi progresif. Tapi, bisa saja akan berubah, toh kekuasaannya baru 7 bulan.
Zaman telah berubah, UGM telah berubah banyak. Saya membayangkan mungkin UGM perlu meneguhkan kembali bahwa UGM sebagai universitas yang independen, berdasarkan lima pilarnya, universitas perjuangan, kerakyatan, nasional, pancasila, dan sebagai pusat kebudayaan. *
Aprinus Salam
Pengajar di Pascasarjana FIB UGM













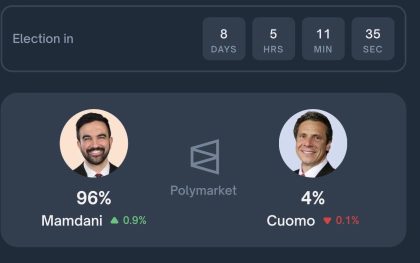


















Komentar