Yanuardi Syukur adalah kandidat doktor Antropologi dari FISIP Universitas Indonesia (UI). Ia adalah dosen tetap Antropologi di Universitas Khairun, Ternate dan pernah aktif sebagai Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Hasanudin (Unhas), Koordinator Kastrat (Kajian Strategis) KAMMI Sulawesi Selatan dan Ketua Bidang Perguruan Tinggi di Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI) di masa kepemimpinan Fahri Hamzah.
Selain mengajar, ia juga pernah diundang mengikuti berbagai program internasional seperti Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (Australia, 2015), Asia-Pacific Think Tank Forum (Bangkok, 2017), U.S. Professional Fellow (AS, 2019), Strategic Equilibrium in the Indo-Pacific short course (Australia, 2023), Indonesian civil society delegation to Ukraine (Ukraina, 2023) dan Diplomasi Budaya Jalur Rempah (Afrika Selatan, 2024).
Dalam ranah akademik, selain menjadi pembicara di beberapa kampus di Indonesia, ia pernah menjadi pembicara pada konferensi/workshop/seminar internasional yang diadakan oleh University of Malaya (Malaysia), Le Havre University & Catholic University of Lyon (Perancis), George Washington University (AS), MGIMO University (Rusia), Griffith University (Australia), Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University (Ukraina), International Peace College South Africa/IPSA (Afrika Selatan), University of Porto (Portugal), dan The Chinese University of Hongkong (Hongkong).
Ia juga menjadi narasumber terkait isu internasional seperti kebudayaan di berbagai negara, terorisme dan konflik & dinamika geopolitik Timur Tengah pada beberapa stasiun televisi seperti TVOne, CNN Indonesia, Trans7, I-News, serta beberapa media seperti China Daily, Times Indonesia, Benar News, etc. Ia merupakan Peneliti pada Negeri Rempah Foundation dan Pusat Riset Timur Tengah dan Islam (IMERC) SKSG UI. Pada 2020, ia mendirikan perkumpulan Rumah Produktif Indonesia (RPI) dan menerbitkan buku terkait G20 dan ASEAN.
Dalam bidang antropologi, ia pernah menjadi tim ahli pada Program Keaksaraan Dasar (belajar membaca & menulis) bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KAT) dan berkunjung ke pedalaman/pesisir pada Suku Anak Dalam (Jambi), Suku Laut (Kepri), Suku Toraja Mamasa (Sulbar), Suku Kajang (Bulukumba), dan Suku Tanimbar (Maluku); menulis beberapa buku literasi di lingkungan Kemdikbud, dan tim revisi buku Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia karya Prof. Melalatoa (editor: Prof. Semiarto Aji Purwanto) di masa Mendikbud Anies Baswedan.
Dalam khidmah-nya di Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, ia terlibat dalam berbagai pembicaraan diplomatik (second track diplomacy) terkait perdamaian dan dunia Islam dengan berbagai diplomat/ulama/cendekiawan (AS, Rusia, China, Australia, Iran, Singapura, Malaysia, Brunei, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Palestina, Oman, Yaman, Turkiye, Mesir, Maroko, Inggris, dan Ukraina), termasuk menjadi tim penyusun Pokok Pikiran MUI terkait penghentian genosida, bantuan kemanusiaan dan dukungan kemerdekaan Palestina untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain itu, ia juga menandatangani seruan penghentian perang Rusia-Ukraina oleh Bandung Spirit Collective & Delphi Initiative for the Defence of Democracy (2022) dan seruan penghentian genosida di Gaza yang ditujukan oleh Amnesty International kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (2025).
Beberapa buku yang ia inisiasi, tulis dan edit adalah Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global (Perpusnas RI, 2022), Recover Together Recover Stronger (Perpusnas RI, 2022) ASEAN Episentrum Pertumbuhan Dunia: Gagasan Konstruktif Masyarakat Indonesia (Mata Kata, 2023), Hidup Damai di Negeri Multikultur (Gramedia, 2017), Muslim Milenial (Mizan, 2018), dan Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia (Australia Awards, 2018). Buku yang ditulisnya mendapatkan penghargaan Pena Award (Bali, 2013). Buku Kisah Negeri-Negeri di Bawah Angin dalam versi Bahasa Inggris—yang ditulisnya bersama tim—mendapat penghargaan Gourmand Award di Saudi Arabia (2023).
Artikel ilmiahnya diterbitkan di prosiding dan jurnal seperti Konferensi Sosiologi (UGM, 2013), 60 tahun Kontribusi Antropologi Indonesia (UI, 2017), Review of Islam in Southeast Asia (UIN Jakarta, 2018), Misykat Al-Anwar (UMJ, 2019), The 2 nd International Conference on Strategic and Global Studies (UI, 2018), Journal of Study Social Politics (UIN Raden Fatah, 2019), Anthropology Online Journal (Antpoj, 2023) dan Theologia (UIN Walisongo, 2024), Buletin Antropologi Indonesia (2024) dan International Journal of Religion (2024). Tulisannya “Family Terrorism – From Family Solidarity and Love to Violence and Hatred” (2022) diterbitkan tiga bahasa (Inggris, Arab, Perancis) oleh Islamic Military Counter Terrorism Coalition, koalisi militer anti-terorisme negara-negara Muslim berbasis di Jeddah, Saudi Arabia.
Perkembangan Terbaru
Founder Erabaru.id (Yons Achmad) berkesempatan mewawancarai sosok ini disela-sela merampungkan studi doktoralnya pada sebuah kafe di Depok (6 Juni 2025). Berikut beberapa buah pikirannya:
Studi doktoral Anda mengkaji soal Antropologi Persahabatan, bisa dijelaskan secara ringkas?
Antropologi persahabatan adalah studi perkembangan dalam Antropologi yang awalnya membahas terkait Antropologi Kekerabatan. Studi ini meneliti persahabatan sebagai praktik sosio-kultural yang dinamis dengan fokus pada bagaimana relasi pertemanan dibangun, dipelihara, dan diberi makna dalam interaksi tersebut.
Dalam disertasi saya, membahas Antropologi Persahabatan sebagai strategi kultural dalam melihat pertukaran kepentingan antaraktor yang mengalahkan primordial interest (kepentingan asal aktor) menuju common interest (kepentingan bersama).
Saya menemukan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, pertukaran kepentingan antaraktor terjadi dalam dimensi emosional, material dan intelektual. Berbeda dengan temuan sebelumnya yang hanya melihat dua dimensi pertukaran, yakni emosional dan material.
Kedua, eksistensi persahabatan tidak hanya dilihat dari partisipasi eksistensial aktor sebagaimana yang dimaksudkan oleh konsep mutuality of being dari Marshall Sahlins, akan tetapi saya memperkaya konsep tersebut dengan konsep baru yakni mutuality of struggling together, yang artinya eksistensi aktor tidak terlepas dari kesediaan aktor untuk berjuang bersama dalam visi yang disepakati.
Studi ini relevan untuk melihat bagaimana aktor-aktor yang berbeda organisasi keIslamannya tapi dapat bersinergi dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Mekanisme kohesinya adalah dengan cara mengalahkan kepentingan primordial atau kepentingan personal keasalan masing-masing dan berfokus pada kepentingan bersama organisasi tersebut. Di situ saya meneliti komunitas (organisasi) Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSIST).
Apakah studi ini juga relavan misalnya untuk membaca organisasi Islam lain semisal Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI)?
KAKAMMI adalah organisasi gerakan Islam yang menarik untuk dilihat. Dalam organisasi tersebut, saya lihat banyak kepentingan aktor yang berkelindan di dalamnya. Agar bisa kohesif, maka organisasi tersebut harus memiliki tujuan bersama (common interest) yang disepakati bersama. Para aktor harus berfokus pada tujuan tersebut dan meminimalisir kepentingan asal masing-masing (organisasi keislaman, partai, etnis).
Interaksi para aktor juga harus terjalin dalam berbagai ‘ritual’, misalnya pertemuan tahunan, diskusi berkala, dan juga yang ringan-ringan seperti ngopi. Ngopi sebenarnya bagian dari “ritual persahabatan” yang dapat menguatkan kohesi antaraktor dan kelak berdampak pada stabilitas organisasi.
Spesifiknya, apakah “Antropologi Persahabatan” ini juga bisa untuk membaca relevansi KAKAMMI sebagai sebuah organisasi agar terus eksis ke depan?
Saya kira bisa. Saya mengkaji tentang fenomena pertukaran antaraktor dalam dimensi emosional, material dan intelektual yang mengalahkan kepentingan personal demi kepentingan bersama.
Antropologi persahabatan dapat digunakan untuk membaca konteks KAKAMMI sebagai berikut. Pertama, alumni KAMMI berasal dari berbagai afiliasi organisasi keislaman. Mereka tidak hanya dari afiliasi jama’ah tarbiyah, tapi juga ada yang secara kultural dan struktural dari NU, Muhammadiyah, PERSIS, PUI, DDII, dan sebagainya. Afiliasi tersebut saya sebagai sebagai ‘organisasi asal’ masing-masing anggota. Sedikit atau banyaknya, organisasi tersebut berpengaruh dalam bagaimana alumni KAMMI berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan.
Kedua, dalam konteks alumni KAMMI yang tidak monolitik itu atau beragam, maka para alumni perlu mencari apa common interest atau kepentingan bersama yang dapat menyatukan semuanya. Kalau dulu di awal-awal KAMMI berdiri, common interest-nya adalah perlawanan terhadap Orde Baru (Pak Harto) dalam gerakan reformasi. Akan tetapi saat ini alumni KAMMI belum menemukan apa ‘isu bersama’ yang dapat menjadi perekat sehingga mereka dapat bersatu dalam satu himpunan.
Menurut saya, common interest bagi alumni saat ini adalah visi Indonesia adil dan makmur yang harus diejawantah dalam berbagai program. Visi ‘adil-makmur’ ini sudah banyak dibahas tokoh, akan tetapi masih belum nampak keadilan dan kemakmuran yang hakiki. Visi ini harus berpijak pada amanat konstitusi, kebijakan pemerintah, dan semangat perubahan yang dilandasi oleh religiusitas Islam yang harus terus hidup dalam diri organisasi dan personal KAKAMMI. []







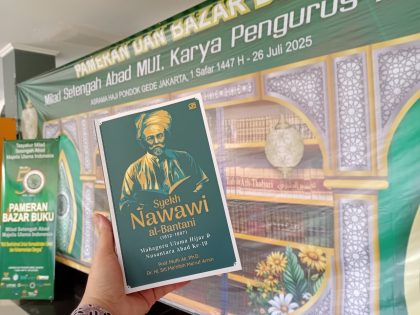








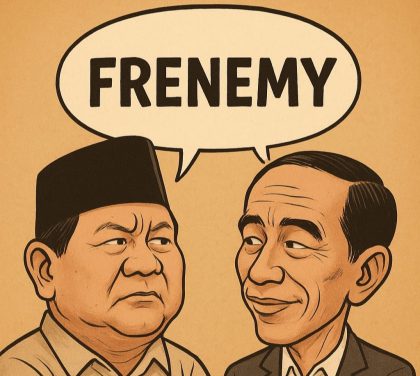
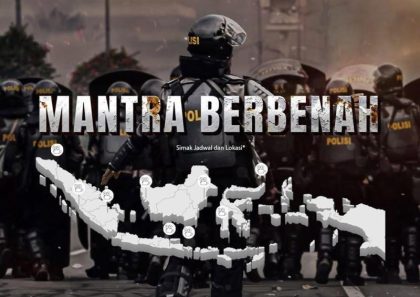












Komentar