Bulan Juni merupakan bulan kelahiran Bung Karno, sekaligus momen pidato Bung Karno tentang Pancasila di sidang Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Kedua momen penting ini dapat menjadi kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan langkahnya dalam mewujudkan Indonesia Maju. Sudah sejalankah langkah yang digagas saat ini dengan semangat yang diajarkan oleh para founding fathers Republik Indonesia.
Pleidoi ”Indonesia Menggugat” yang disampaikan Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial tahun 1930 mengandung beberapa poin yang masih relevan hingga saat ini.
Sukarno memanfaatkan momen tersebut guna melontarkan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang mengisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis. Sukarno menyebutnya sebagai politik drainage.
Kebijakan imperialis, menurut Sukarno, merupakan penyebab kesengsaran bangsa Indonesia. Sukarno menyebutkan bahwa akibat politik drainage, tiap rumah tangga ”marhaen” hanya mendapatkan 138,50 gulden per tahun atau 0,40 gulden per hari.
Kesengsaran itulah yang melahirkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial, bukan karena hasutan kaum pergerakan. Indonesia telah merasakan era kemerdekaan selama 79 tahun dan telah berlalu pula 95 tahun pasca-pleidoi Indonesia Menggugat, akan tetapi gugatan Bung Karno terhadap kebijakan ekonomi eksploitatif masih terasa gaungnya hingga saat ini.
Hal ini kemudian diingatkan kembali oleh Presiden Prabowo pada peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika di Universitas Pertahanan, 11 Juni 2025. Selama menjajah Indonesia, Belanda telah mengambil keuntungan setara 31 triliun dollar AS (setara Rp 511.000 triliun), yang berarti sama dengan jumlah APBN selama 141 tahun.
Sayangnya, pola ekonomi ekstraktif yang jadi musuh rakyat Indonesia di era kolonial belum benar-benar hilang hingga saat ini. Data Bank Dunia mencatat pertambahan penduduk miskin dari 46,1 persen di 2017 menjadi 49,8 persen di 2023. Penduduk kelas menengah juga turun dari 23,1 persen menjadi 17,4 persen. Padahal, pada saat bersamaan ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan.
Di sisi yang lain, di tengah naiknya angka kemiskinan, Forbes Global Wealth Report justru mencatat adanya pertambahan 100 persen dari nilai kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia dari 2017 ke 2023.
Ekonomi ekstraktif oleh kolonial yang menghasilkan kepedihan bangsa Indonesia sesungguhnya disikapi BPUPKI dengan memasukkan ekonomi kerakyatan pada UUD 1945 pada Pasal 33 sebagai landasan konstitusi bagi sistem ekonomi nasional. Disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Pada ayat kedua, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Serta di ayat ketiga, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adanya pasal ini seharusnya menjadi antitesis kebijakan ekonomi eksploitatif yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Sejatinya kekayaan alam Indonesia harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak saja.
Belum terciptanya pertumbuhan ekonomi yang benar-benar merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia menandakan adanya missing link antara falsafah ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan pelaksanaannya hingga saat ini. Paling tidak ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya hal ini.
Pertama, adanya kroniisme antara negara dan pelaku usaha yang membuat penguasaan kekayaan alam hanya dimanfaatkan segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri. Kedua, ekonomi ekstraktif yang hanya menjual kekayaan alam sebagai bahan mentah tak dapat memberikan kemakmuran kepada lebih banyak rakyat.
Gejala pertama bisa diatasi melalui transparansi dan penegakan hukum konsisten dan tak pandang bulu. Pejabat negara perlu memiliki integritas dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.
Gejala kedua harus diatasi melalui penguatan kemampuan industri dalam negeri guna mengolah kekayaan alamnya sendiri. Dengan demikian, akan lebih banyak rakyat terlibat dalam proses produksi dan menambah nilai ekonomi secara signifikan melalui hilirisasi.
Upaya reindustrialisasi
Industri merupakan pendorong utama pertumbuhan negara-negara di dunia. Beberapa negara Asia yang sama-sama baru merdeka di sekitar 1945 mengalami pertumbuhan signifikan melalui jalur ini.
Sebut saja Jepang dan Korea yang saat ini berstatus sebagai negara maju, memulai perjuangannya dari nol hampir bersamaan dengan Indonesia. China menjadi negara besar selanjutnya yang melakukan industrialisasi hingga sekarang hampir masuk ke dalam negara maju berpendapatan tinggi.
Kondisi China sebenarnya serupa Indonesia dalam aspek kekayaan sumber daya alam (SDA). China memiliki kekayaan berupa cadangan mineral tambang yang bisa dimanfaatkan. Namun, China tak serta-merta menjual kekayaan itu ke luar sebagai bahan mentah begitu saja. China juga memiliki basis industri kuat guna mengolah bahan mentah tersebut.
Perjalanan China menjadi negara industri terbesar dunia dimulai lewat pengembangan industri pengolahan besi dan baja, kimia, smelter bahan tambang, batubara, dan permesinan.
China menerapkan perencanaan ekonomi berjangka yang pernah diterapkan Indonesia di masa Orde Baru sebagai rencana pembangunan lima tahun (repelita). Mayoritas industri yang didorong China di tahap awal merupakan industri dasar yang didominasi oleh BUMN.
Barulah di tahap akhir mulai bermunculan industri swasta pada bidang elektronik, teknologi yang berorientasi pasar global. Kontribusi industri China terhadap PDB hingga saat ini masih cukup tinggi di atas 30 persen, bahkan di era 2000-an awal sempat berkontribusi di atas 40 persen terhadap PDB.
Sebagai perbandingan, kontribusi sektor industri Indonesia terhadap PDB di 2024 tercatat 19,02 persen. Kontribusi industri terhadap PDB pernah di angka 32 persen pada 2002.
Berkurangnya kontribusi sektor industri dan menguatnya sektor jasa sebenarnya wajar di negara maju. Namun, kondisi Indonesia saat ini masih belum mencapai derajat negara maju berpenghasilan tinggi. Sektor industri merupakan penggerak penting sebab hingga saat ini pun sektor ini merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Indonesia.
Apa yang menyebabkan perkembangan industri di Indonesia tidak bisa sepesat China, meski sama-sama memulai pembangunan industri melalui repelita di saat yang hampir bersamaan? Hal pertama yang bisa langsung diidentifikasi tentu penerapan repelita di Indonesia sudah terhenti sejak berakhirnya Orde Baru.
Beberapa industri strategis, seperti industri baja yang menjadi industri dasar, tidak mendapat perhatian dan kini sudah tidak lagi kompetitif.
Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara sudah memiliki rencana, salah satunya memperkuat kembali sektor-sektor industri dasar melalui kebijakan hilirisasi.
Danantara dapat mengambil peran strategis dalam melakukan investasi pembangunan industri dasar pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku yang selama ini masih lambat pertumbuhannya. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia memiliki fondasi industri yang lebih kuat dan lebih diminati untuk investasi di sektor industri lanjutan.
Sains dan teknologi, kunci industri maju
Hal kedua adalah dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mendukung iklim industri di Indonesia tidak sekuat di China.
Dalam sebuah wawancara, CEO Apple Tim Cook pernah menyampaikan alasan mengapa Apple menempatkan produksinya di China. Keputusan itu bukan semata-mata karena murahnya ongkos buruh di China, tetapi karena China memiliki stok SDM dengan kemampuan teknis yang sangat memadai.
Cook menggambarkan kualitas pekerja manufaktur China yang memiliki perpaduan antara penguasaan keterampilan (skill) pertukangan tinggi, penggunaan robotika dan sains komputasi yang canggih. Kombinasi ini sangat jarang ditemukan di negara lain di dunia.
Guna memenuhi kualifikasi SDM industri seperti digambarkan, Indonesia perlu membenahi pendidikan serta penguasaan sains dan teknologi.
Sektor industri merupakan sektor yang membutuhkan skill spesifik yang hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang spesifik. Industri tidak bisa disuplai oleh lulusan pendidikan yang bersifat umum. Jika ingin mendorong industri pengolahan logam, pendidikan teknik metalurgi dan material perlu disiapkan. Demikian juga industri elektronika yang perlu lulusan di bidang teknik elektronika dan seterusnya.
Setiap tingkatan kompleksitas industri juga membutuhkan kualifikasi lulusan yang berbeda. Ada beberapa industri yang membutuhkan banyak pekerja dengan kualifikasi sekolah vokasi atau SMK. Namun, industri kompleks seperti elektronika, pemurnian logam, atau semikonduktor, butuh kualifikasi lulusan yang jauh lebih tinggi.
Jika industri semikonduktor ingin membuka unit produksi, minimal harus tersedia lulusan sarjana yang spesifik. Jika industri ini ingin dijadikan pusat riset dan pengembangan teknologi dengan nilai investasi yang jauh lebih besar tentu harus ada lulusan dengan kualifikasi pascasarjana bahkan doktoral dalam jumlah yang cukup.
Jangan heran jika beberapa industri besar berbasis teknologi tinggi nampak sulit berinvestasi di Indonesia. Selain mempermuah berbagai perizinan dan regulasi yang ada, Indonesia juga harus benar-benar menyediakan tenaga kerja dengan kemampuan spesifik dalam jumlah memadai.
Pada aspek ini akhirnya industri memutuskan untuk memilih negara lain sebagai tempat investasi karena memiliki stok SDM yang lebih siap.
Global Innovation Index dapat memberikan gambaran mengapa negara tetangga Indonesia masih lebih diminati sebagai tempat investasi industri. Pada peringkat GII, Indonesia berada di peringkat 54, masih kalah dari Singapura, Vietnam, bahkan Thailand, Filpina, dan Malaysia.
Indeks ini mengukur kesiapan Indonesia dalam mengembangkan inovasi serta industri berbasis teknologi tinggi. Beberapa penilaian GII mencakup kesiapan infrastruktur dan SDM. Kondisi ini tentu menjadi bahan introspeksi serta pekerjaan rumah bagi kita semua.
Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sumber. Kompas 3 Juli 2025)










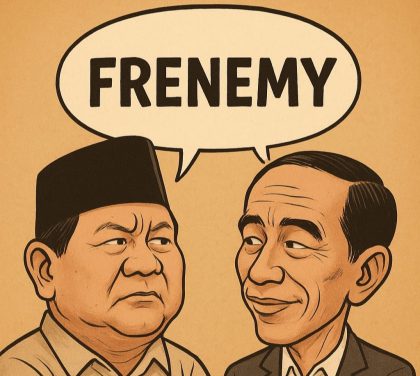
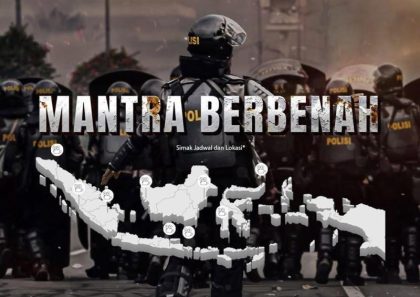












Komentar