Misi besar Ihya’ ‘Ulumiddin, kata Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, adalah untuk membenahi kerusakan ilmu-ilmu agama supaya kembali “hidup”. Ilmu-ilmu itu rusak karena para ulamanya rusak. Mereka rusak karena cinta dunia. Merekalah para pengingkar ilmu-ilmu agama yang hendak direspons Imam Ghazali melalui Ihya’.
Dalam pendahuluan Ihya’, kitab yang ditulisnya di masa-masa akhir ‘uzlahnya (sekitar tahun 1100-an M), Imam Ghazali menuturkan bahwa di masa itu, ilmu-ilmu agama telah kehilangan tujuan hakikinya.
Kala itu, yang disebut “berilmu” di tengah pelajar-pelajar Islam, adalah mereka yang ahli berfatwa sekalipun menyesatkan, lihai berdebat demi mengalahkan orang lain, indah bersajak walau tanpa makna bahkan diiringi dosa.
Luput dari mereka pandangan Islam terhadap ilmu, bahwa ilmu harus diamalkan, digunakan untuk lebih taat kepada Allah supaya semakin dekat, dimiliki untuk menyucikan dan membenahi hati, digunakan untuk memperjuangkan dan membela Islam.
Hilang dari pikiran mereka peringatan Nabi bahwa “manusia yang paling keras azabnya adalah orang-orang berilmu yang Allah tidak buat ilmunya bermanfaat.” Arah ilmu-ilmu mereka, melulu soal dunia dan pernak-perniknya.
Ilmu-ilmu yang rusak karena telah kehilangan arah itu, kata Imam Ghazali, diproduksi massal oleh para ulama “gadungan” yang tidak layak disebut sebagai “pewaris Nabi”. Mereka yang begitu mudah mencintai dunia dan dikuasai oleh setan; rela menyerahkan dirinya sebagai pelayan penguasa.
Akhirnya, yang benar ditolak dan yang salah dipuja, yang tidak sejalan sedikit saja dengan mereka dicela habis-habisan. Demi jabatan dan harta, mereka bisa dengan mudahnya menyulap yang ma’ruf menjadi munkar, dan munkar menjadi ma’ruf.
Kerusakan mereka pun kemudian menular kepada orang-orang awam melalui ilmu-ilmu rusak yang diajarkan itu. Begitulah kata Imam al-Ghazali ilmu-ilmu agama di masa itu benar-benar telah pudar, kehilangan cahayanya; “Menara petunjuk” telah redup untuk waktu yang lama.
Kalau fenomena ini dibiarkan terjadi, agama Islam bisa terancam “hilang”. Kata Imam al-Ghazali, ia ibarat lubang di satu kapal besar, yang jika dibiarkan, dapat menenggelamkan kapal besar itu, beserta para penghuninya. Terlebih, para ulama sejati selaku pewaris Nabi, perlahan, sudah mulai hilang ditelan zaman, membuat umat kehilangan pegangan.
Imam Al-Ghazali menyadari bahwa mereka, baik para ulama maupun orang awamnya, dapat berpandangan demikian karena tidak lagi memandang agama sebagai asas dan tujuan tertinggi dalam hidup. Agama tidak dirasakan lagi sebagai perkara yang serius. Begitu pula pandangan terhadap akhirat yang pasti datang dan dunia yang pasti hilang.
Maka dengan tegas Imam al-Ghazali katakana bahwa tujuan utama ia menulis Ihya’ adalah untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dibuat mati terkapar oleh para pemuka agama “palsu”, menyingkap manhaj ulama-ulama sejati terdahulu, dan menjelaskan ilmu-ilmu yang bermanfaat (hakikat ilmu) menurut Nabi dan para ulama salaf.
Fenomena kerusakan ilmu dan ulama di masa Imam Al-Ghazali itu masih terus terjadi hingga hari ini dan menjadi sorotan. Salah satunya intelektual besar Islam yang menyoroti kekacauan ilmu (confusion of knowledge) adalah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Ia menyebutnya sebagai tantangan terbesar (the greatest challenge) bagi umat Islam hari ini.
Bahkan menurutnya, kini, tantangan itu jauh lebih komprehensif karena masifnya paham Sekularisme yang dipasarkan Peradaban Barat. Ilmu yang dibuat rusak olehnya, dapat membuat orang Islam memandang Tuhan dan agama tidak penting, menolak kemutlakan nilai, mengingkari Allah dan hari akhir, memuja dunia, menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan, dan membawa kekacauan pada alam semesta (Al-Attas, Islam and Secularism, 1993).
Mohammad Natsir mengatakan hal yang senada, bahwa Sekularisme hanya akan menimbulkan “taufan ruhani”, erosi keyakinan, melonggarkan nilai-nilai akhlak, membuat tidak bangga dengan Islam dan mengidap penyakit “wahn”: cinta dunia dan takut menghadapi risiko sehingga malas berjuang serta kehilangan kepekaan terhadap masalah-masalah umat (M. Natsir, Pesan Perjuangan Seorang Bapak, 2019 & Islam Sebagai Dasar Negara, 1957).
Begitulah kerusakan ilmu melahirkan apa yang Al-Attas sebut sebagai “loss of adab.” Kalau kondisi ini dibiarkan, akan lahir para pemimpin palsu (the false leaders), khususnya pemimpin dalam ranah keilmuan (termasuk ilmu-ilmu agam), yang akan menyuburkan dua problem itu.
Maka pandangan Sekularisme yang berjalan beriringan dengan jiwa cinta dunia, masih bertanggung jawab penuh atas rusaknya ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Natsir menggambarkan betapa peliknya pikiran dan moral manusia ketika pikiran dan jiwanya benar-benar sudah dibutakan oleh dunia:
“Bagi orang yang dihinggapi penyakit ‘hubungannya’ itu seluruh fikiran dan keinginannya ditujukan untuk menikmati kesenangan duniawi semata-mata. Candu senang yang tidak mengenal batas dan tak mengenal puas. Ibarat orang minum air laut, semakin diminum semakin dahaga. Tak ada baginya diskriminasi antara kesenangan yang pantas dan bersih, dengan ‘kesenangan’ yang tak wajar dan merusak. Jangan dicoba menyebut istilah ‘halal’ dan ‘haram’. Pemisahan-pemisahan seperti itu dianggap sebagai tradisi kuno, sudah ‘out of date’, tak laku lagi di abad ke-20 ini, dan lantaran itu perlu diganti dengan norma-norma bikinan sendiri yang menurut seleranya lebih ‘up to date’. Tak usah pula dibaca-baca masalah ‘malu’ di depannya.
‘Rasa malu’ untuk berbuat sesuatu yang selama ini dipandang melanggar kesopanan, dianggap sebagai ciri ‘keterbelakangan’, malah sebagai ciri nifaq ‘hipocrisy’… bertindak dan berlaku seenaknya sendiri, ‘semau guwe’, kapan dan dimana ia senang, dianggap sebagai satu kejujuran (honesty), sebagai ciri ‘kebudayaan’ dan kemajuan yang terpuji di zaman modern ini. Dengan lain perkataan: satu-satunya nilai hidup yang dituju dan dipujanya di dunia ini ialah kesenangan jasmaniyah, ‘material comfort’. Ke arah inilah seluruh angan-angan, tenaga dan kepintarannya ditujukannya. Tak ada lagi nilai selain daripada itu. Jiwanya kosong dari sesuatu yang berupa idealisme untuk mana seseorang rela menderita dan berkorban untuk mencapainya” (Natsir, “Idul Fihtri: Forum Instospeksi”, dalam majalah Suara Masjid, No. 131, 1985).
Melihat betapa relevannya isi Ihya’ dengan problematika umat Islam hari ini, maka mengkaji Ihya’ Ulumuddin di masa ini menjadi begitu penting. Hal ini ditegaskan pula oleh Wan Suhaimi Wan Abdullah dalam bukunya, Khulasah Faham Ilmu:
“Antara keistimewaan Ihya’ adalah ia mengemukakan suatu kaedah pemikiran dan kerangka penyelesaian yang menyeluruh bagi pelbagai permasalahan keilmuwan, pemikiran, keruhanian serta hala tuju kehidupan umat Islam… Tidak keterlaluan jika ditegaskan bahawa persekitaran yang melatarbelakangi Ihya’ banyak persamaannya dengan apa yang dihadapi oleh umat Islam kini. Golongan yang dikelompokkan sebagai ilmuwan kini, ramai yang keliru, apatah lagi di dalam kalangan orang awam.
Pemahaman dan tafsiran Islam secara terpisah tanpa sebarang kerangka kesatuan menjadikan pemahaman dan amalan Islam sempit. Penekanan terhadap persoalan hukum-hakam secara tidak adil dan tepat, kecenderungan memperdebatkan masalah-masalah yang tidak menyumbang kepada pembangunan ilmiah dan pengamalan Islam yang sempurna, ditambah pula dengan kecenderungan pendekatan retorik yang berlebihan dengan slogan-slogan kosong banyak menyumbang kepada keadaan ini.
Akhirnya kekeliruan dalam pelbagai sudut kehidupan berleluasa atas nama ilmu. Tambahan pula, para ilmuwan pewaris Nabi s.a.w. sudah berkekurangan, sebaliknya para ulama jadian dan ulama dunia diangkat memimpin. Ini telah berlaku di zaman al-Ghazali sekitar 1000 tahun dahulu. Dan, pastinya ia lebih parah pada masa kita kini… Judul Ihya’ ‘Ulum al-Din sendiri jelas menggariskan matlamat penulisannya iaitu untuk menghidupkan kembali pemahaman dan peghayatan ilmu agama yang ‘mati’ akibat kekeliruan para ilmuwannya”.
Fatih Madini (Alumni STID Mohammad Natsir)













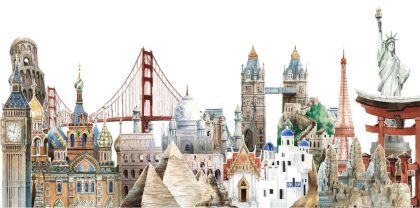









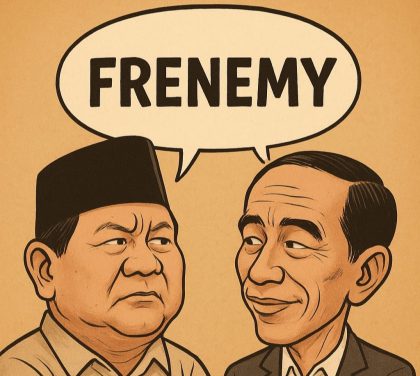
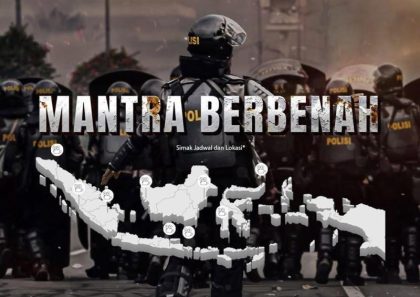











Komentar