Pahlawan Nasional Mohammad Natsir menjelaskan, pada dasarnya, masyarakat punya hajat terhadap seorang pemimpin “untuk menjamin terlaksananya segala sesuatu, bagi keselamatan atau kesejahteraan masyarakat dan para anggautanya.”
Tapi hajat itu akan sulit diwujudkan ketika ia berjalan tanpa ada tuntunan yang jelas dan “kuat”. Sebab, tanpanya, dapat muncul penguasa-penguasa yang tidak diridhai oleh rakyatnya karena zalim, berlaku semena-mena dengan kekuasaannya kepada mereka (M. Natsir, Fiqhud Da’wah, 200).
Maka, kata Natsir, Islam hadir dengan meletakkan kedaulatan “Undang-Undang Ilahy” pada kedudukan tertinggi—sebagai “Undang-Undang yang memberi kata putus dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, ‘point of reference’, tempat memulangkan persoalan”—dan loyalitas kepada Allah dan Nabi Muhammad pada posisi tertinggi.
Karenanya, akan lahir para penguasa yang begitu adil kepada rakyatnya—yang tidak hanya mengeluarkan kebijakan terkait pemberantasan korupsi, perlindungan mati-matian terhadap fakir miskin, penggalakan pendidikan, pemerataan ekonomi masyarakat, tapi juga pencegahan perzinaan dan minum minuman keras (khamr)—sehingga ia pun ditaati oleh rakyat-rakyatnya.
Sebab, kata Natsir, dalam Islam, “Imbangan dari wajib ta’at kepada Ulil-Amri adalah sama-sama wajib taatnya Ulil Amri kepada Allah dan Rasul, wajib sertanya menjaga amanat kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.” Jadi, semakin loyal dan taat seorang pemimpin kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin peduli dan adil ia kepada rakyat-rakyatnya demi kesejahteraan mereka (QS. An-Nisa’: 59).
Hal ini pun turut berpengaruh baginya dalam memutuskan sebuah kebijakan, yaitu melalui jalan musyawarah atau demokratis (QS. Al-Syura: 38) dengan mengedepankan kesadaran bahwa dirinya adalah sebagai pemimpin yang membawa beban amanah bagi rakyat (QS. An-Nisa’: 58 dan Ali-Imran: 159) (M. Natsir, Peranan Islam dalam Pembinaan Demokrasi).
Soal musyawarah, Natsir menegaskan, “… adalah satu ketentuan dalam adjaran Islam supaja dalam mengatur urusan jang mengenai orang banjak itu si penguasa harus memperoleh keridlaan dari pada orang jang diaturnja dan harus ia me-musjawaratkan segala sesuatu jang mengenai perkehidupan dan kepentingan rakjat banyak… terdapat banjak sekali tjontoh jang diberikan oleh Nabi Besar Muhammad saw, dan para Sahabatnja, pada masa seluruh dunia pada waktu itu tenggelam di dalam alam despotisme, feodalisme, oligarchie dan diktatur” (Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara, 1957)
Dengan musyawarah, keputusan yang diambil, kebijakan yang dirumuskan dan diputuskan akan bisa lebih bijaksana sebagaimana tercantum dalam sila keempat dari Pancasila (M. Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, 2001)
Hanya saja, Natsir mengingatkan, yang perlu dimusyawarahkan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan segala hal yang prinsip dalam agama, termasuk soal dasar bagi pemerintahan (Islam):
“… tidaklah perlu dipermusjawaratkan terlebih dulu, apakah jang harus mendjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keridhaan parlemean terlebih dulu, apakah perlu diadakan pembasmian arak atau tidak, apakah perlu diadakan penghapusan perdjudian dan ketjabulan apa tidak, apakah perlu diadakan pemberantasan churafat dan kemusjrikan atau tidak… Adapun prinsip dan qa’idahnja sudah tetap, tidak boleh dibongkar-bongkar lagi.”
Begitulah sifat demokratis Islam yang berarti anti absolutisme, kesewenang-wenangan dan kediktatoran namun tetap berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (Natsir, Islam Sebagai Ideologie).
Wujud pemimpin adil yang lahir melalui tuntunan wahyu tampak (misalnya) dalam diri Sahabat Nabi, Abu Bakar, ketika memberi pidato usai dilantik sebagai Khalifah:
“Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah dipilih untuk memegang kekuasaan atasmu, padahal aku bukan yang terbaik di antaramu; Maka jika kau berlaku baik (dalam menjalankan kekuasaan itu) bantulah aku; tetapi jika salah, betulkanlah. Kejujuran adalah amanah, dusta adalah khianat. Barangsiapa yang lemah antaramu akan kuat bagiku, sehingga aku kembalikan haknya (dari tangan orang lain yang memegangnya) insya’ Allah; Barangsiapa yang kuat di antaramu akan lemah berhadapan denganku, sehingga aku ambil hak orang lain dari tangannya, insya Allah. Taatilah aku, selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya; Apabila aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, tidak ada atasmu wajib taat kepada-ku” (Natsir, Fiqhud Da’wah).
Karena tunduk terhadap Undang-Undang Ilahi dan loyal kepada Allah, seorang penguasa akan dengan mudah menerima kedaulatan hukum secara objektif. “Menurut syari’at Islam: Hukum berdaulat atas semua anggauta masyarakat dari yang selemah-lemahnya, sampai kepada Uli’l-amri yang paling tinggi. Semuanya berkedudukan sama di hadapan Hukum… tidak ada keistimewaan lantaran pangkat, keturunan atau ‘social-standing, kedudukan dalam masyarakat,” ucap Natsir merujuk Surat An-Nisa’ ayat 135.
Begitulah menurut Natsir, sifat pemimpin yang bertaqwa, yang “mampu mengendalikan dirinja dari hawa dan nafsu, dalam menegakkan keadilan… tidak pilih bulu, tidak tergantung kepada senang atau tidak senangnja ‘like’ atau dislike’ dia sendiri terhadap orang jang bersangkutan,” sebagaimana tersirat dalam Surat Al-Maidah ayat 8.
Bagi Natsir, setidaknya, dua ayat itu dapat mendorong lahirnya para pemimpin, dalam aspek apa pun khususnya politik, yang “menegakkan keadilan atas nilai-nilai moral jang universal, orang bertaqwa tidak kenal apa jang disebut dubbel moral, sebagai ukuran. Moral ‘bermuka-dua’, moral serba-muka jang kesudahannja mendjadi moral kosong dan hampa.” Prinsip mereka, “adil adalah adil, tidak ibarat kata orang: ‘tiba dimata dipedjamkan, tiba di perut dikempiskan,” tegas Natsir (M. Natsir & Sjafruddin Prawiranegara, Chutbah-Chutbah Idul Fithri 1387, 1968).
Khalifah Umar bin Khattab telah lama menampilkan sifat ini:
“Diriwayatkan bahwa Raja Ghassan datang mengunjungi Khalifah Umar bin Khattab. Di tengah-tengah orang ramai terpijak baju Raja yang panjang berjelo-jelo itu oleh seorang rakyat biasa. Raja Marah, lalu ditamparnya yang menginjak bajunya. Si rakyat mengadukan halnya kepada Khalifah. Di waktu Khalifah menjatuhkan hukuman yang sewajarnya kepada Raja Ghassan berkenaan dengan insiden itu, sang Raja bertanya: ‘Kenapa begitu ya Amiral Mu’minin, bukannya aku ini Raja, dan dia hanya seorang rakyat biasa?’ Khalifah menjawab… ‘Sesungguhnya Islam telah menghimpunkan tuan-tuan kedua-duanya, dan menempatkan seorang Raja dan seorang rakyat biasa dalam taraf yang sama di depan hukum!’…
Risalah mengatakan… ‘Dengarkanlah dan ta’atilah! Sekalipun, andai kata yang menjalankan hukum atasmu seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis (buah anggur kering), selama yang dijalankannya hukum (Kitab) Allah s.w.t.’ (Sahih Bukhary). Cinta kepada keadilan dan rasa hormat kepada kedaulatan hukum dan kemerdekaan hukum ini, demikian mesranya hidup dalam qalbu Ummat Muhammad s.a.w. sehingga khalifah Umat bin Khattab (r.a.) tidak segan-segan menghadap mahkamah yang dibentuknya sendiri untuk mengadili perkara atas tuntutan seorang rakyat biasa. Dia rela menerima keputusan hakim. Dan hakim tidak ragu-ragu menjatuhkan ponis walaupun terhadap Kepala Negaranya. Hakim merdeka. Hukum berdaulat” (Natsir, Fiqhud Da’wah).
Fatih Madini (Alumni STID Mohammad Natsir)






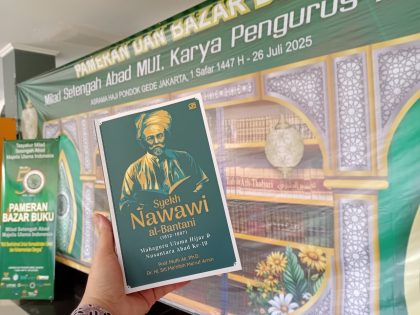























Komentar