Affan Kurniawan adalah pemuda biasa. Saya yakin, dia adalah sesederhana-sederhananya rakyat Indonesia. Mimpinya mungkin tidak muluk. Ia hanya ingin kebutuhannya tercukupi saat ini dan bisa membangun masa depan. Keinginan yang tidak terlalu mewah.
Hari ini kita tahu bahwa nasib Affan menjadi lain. Seperti banyak rakyat yang merasakan semakin sulitnya mencari kehidupan saat ini dan suramnya masa depan, ia ada di kalangan demonstran yang berunjuk rasa bersama buruh. Demo ini ditanggapi dengan brutalitas yang berlebihan oleh polisi.
Video kematian Affan sontak beredar luas. Dia dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob setelah sebelumnya ditabrak kendaraan yang sama.
Terlalu sering kita melihat polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) untuk menangani demonstrasi. Tindakan brutal seolah sudah menjadi SOP kepolisian. Polisi kemudian mencari kambing hitam atas brutalitas yang mereka lakukan, yaitu anak-anak Anarko.
Beberapa kali sayga melihat kebrutalan seperti ini. Kadang saya bertanya: Tidakkah mereka punya standar moral? Mengapa mereka mengaku berpegang pada ajaran agama? Bahkan ada teman yang sinis mengatakan, kalau beragama mereka tidak akan jadi polisi! Sedemikian rendah kepercayaan masyarakat pada lembaga ini.
Sebagai orang yang sudah dewasa pada era 1990an, saya masih ingat persis betapa bencinya orang saat itu kepada militer karena mereka sangat brutal. Polisi saat itu tidak sebrutal militer yang memiliki PHH (Pasukan Anti Huru Hara) untuk menjaga rejim Suharto. Anehnya Suharto pun jatuh karena huru hara.
Seperti polisi sekarang, PHH dilengkapi tameng dan gas air mata. Namun yang paling menakutkan brutalnya adalah tentara dengan motor trail untuk memecah barisan demonstran. Itu persis taktik polisi saat ini. Hanya saja lebih horor. Mereka tidak hanya memakai motor trail tapi juga Rantis alias kendaraan taktis.
Saya pernah agak serius belajar tentang gerakan sosial dan kepolisian (policing) ini. Satu hal yang saya ingat adalah bahwa antara demonstran dan polisi itu ada hubungan aksi-reaksi. Para pendemo akan beraksi atas aksi polisi. Dan polisi pun bereaksi terhadap tingkah pendemo.
Penggunaan kekerasan oleh polisi akan memancing penggunaan kekerasan oleh massa. Polisi yang menggunakan kekerasan dengan tujuan membikin massa takut, sudah hampir pasti akan menuai reaksi balik — yang akan membuat polisi itu juga takut dan makin menggunakan kekerasan hingga ke tingkat brutal. ini adalah spiral kekerasn.
Polisi-polisi Inggris terkenal dengan kemampuannya mengontrol massa dengan tangan kosong. Mereka bukan ahli silat atau bela diri. Namun mereka berusaha tampil kalem, profesional, tidak takut, tapi tegas dan mampu berdiplomasi dengan massa. Ketiadaan senjata membuat massa menjadi lebih tenang. Ketiadaan ketakutan membuat massa bisa diajak berdialog. Unjuk rasa pun kerap menjadi ajang beriang gembira sambil tetap menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
Di negeri ini, polisi tampil garang. Tujuannya supaya ditakuti dan disegani. Tidak ada unsur keinginan untuk berdialog dengan masyarakat. Kadang hal yang menakutkan itu dilakukan dengan cara seperti maling: dia bersembunyi di tikungan supaya bisa menangkap pelanggar lalu lintas! Cara-cara maling yang manipulatif seperti ini akan membuat refleks mekanisme pertahanan diri masyarakat biasa. Mereka juga akan berusaha mengakali polisi. Dan bilamana ada kesempatan mereka akan menyerang balik polisi.
Penggunaan kekuatan secara berlebihan akan ditanggapi massa dengan kekerasan. Situasi di saat demo itu sebenarnya sangat mirip dengan peperangan. Sedikit saja salah baca (misperception) antara polisi dan massa maka situasi akan menjadi kacau. Policing yang baik adalah berusaha menghindari misperception atau salah paham. Situasi ini persis seperti situasi awal mulainya peperangan.
Untuk soal kebrutalan polisi yang sangat tidak manusiawi ini, saya ingat akan buku Hannah Arendt, On Violence (Tentang Kekerasan). Dalam buku itu, seingat saya Arendt menulis bahwa baik penguasa maupun yang dikuasai harus berdiri pada standar moral yang sama.
Apakah yang terjadi kalau gerakan Ahimsa-nya Mahatma Gandhi dihadapi BUKAN oleh penguasa Inggris? Misalnya Ahimsa-nya Gandhi berhadapan dengan Kopassus-nya Prabowo pada tahun 1990an? Seperti Arendt, saya yakin, Kopassus-nya Prabowo akan menghabisi Ghandi dan pengikutnya tanpa ampun. Keduanya tidak berada dalam standar moral yang sama.
Pada tataran yang sama, seberapa pun saat ini Anda menginginkan aksi tanpa kekerasan, Anda mau tidak mau harus berhadapan dengan aparat-aparat yang tidak memiliki standar moral yang sama seperti Anda. Aparat-aparat ini akan menghajar Anda tanpa ampun sekali pun Anda tidak melakukan agresi atau perlawanan.
Itulah yang menjelaskan mengapa tragedi Affan Kurniawan ini terjadi. Penguasa di negeri ini memang melatih para penjaganya untuk brutal dan sama sekali tidak manusiawi. Sekalipun sebenarnya ada cara-cara yang jauh lebih manusiawi, yang menghormati martabat manusia.
Itu tidak akan dilakukan oleh aparat-aparat ini! Kita tentu tahu bahwa brutalitas ini untuk mengamankan mereka yang tidak tersentuh oleh apapun. Mereka yang bisa berbuat apa saja yang mereka inginkan, mengambil apa saja yang mereka butuh atau tidak butuhkan.
Jangan menangis melihat kekerasan ini. Ini hanya permulaan. Yang lebih massif akan datang. Karena mereka tidak memiliki legitimasi untuk berkuasa dan satu-satunya cara memempertahankan ini adalah dengan bertindak brutal.
Hanya dengan brutalitas yang luar biasa menjijikkan ini, orang seperti Ahmad Sahroni bisa terus menerus berkokok jumawa. Dia tidak satu-satunya, tapi hampir semua elit di negeri ini sejumawa dia dan Sudewo dari Pati itu.
Made Supriatma










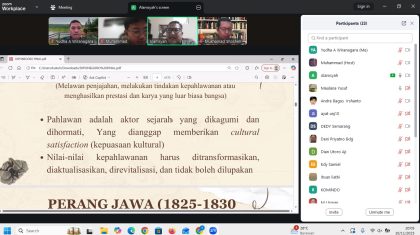


















Komentar