Di zaman sekarang ini, politik tak lagi hanya berlangsung di gedung parlemen atau rapat kabinet. Ia hidup di layar ponsel kita. Foto, video, meme, hingga siaran langsung menjadi medan pertarungan siapa yang berhak menentukan makna peristiwa. Narges Bajoghli (2023) menyebut era ini sebagai pertarungan visualitas, yakni siapa yang boleh terlihat, siapa yang sengaja disembunyikan.
Kita bisa melihatnya dengan jelas dalam demonstrasi besar di Nepal, September 2025. Pemerintah menutup 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, Whatsapp, dan X atau Twitter, untuk meredam keresahan, tetapi justru memicu letupan yang lebih dahsyat. Bagi generasi muda Nepal, media sosial bukan sekadar tempat hiburan, tetapi ruang hidup, sebuah ‘tempat nyaman’ mereka belajar, bekerja, dan membangun identitas. Ketika ruang itu dirampas, amarah pun meluap. Itu jelas, karena media sosial adalah bagian dari kehidupan anak muda sekarang yang hanya bisa diatur, tapi tidak bisa dirampas.
Hal menarik dari protes itu tak hanya menampilkan tuntutan politik, tetapi juga simbol-simbol budaya. Bendera One Piece berkibar di tengah massa—ini juga terjadi di Indonesia dalam demonstrasi baru-baru ini. Sebuah ikon pop global kemudian dipinjam untuk menegaskan identitas kolektif anak muda yang menolak bungkam. Sepertinya, inilah yang dimaksud Robert Gibb (2001), bahwa gerakan sosial bukan sekadar reaksi spontan, melainkan praktik budaya-politik. Ia lahir dari perpaduan ekonomi, simbol, dan identitas yang bersama-sama membentuk solidaritas untuk bersiasat secara kolektif.
Fenomena serupa kita jumpai di Indonesia pada Agustus–September 2025. Awalnya publik geram melihat tunjangan rumah anggota DPR yang fantastis sebesar Rp50 juta per bulan. Tetapi kemarahan berubah menjadi gelombang besar setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, tewas tertabrak kendaraan taktis polisi. Video dan foto peristiwa itu menyebar luas, menjelma simbol ketidakadilan yang mengguncang hati rakyat. Di saat yang sama, beredar pula rekaman anggota DPR berjoget riang di tengah krisis. Kontras inilah yang membuat publik kian murka.
Di sinilah konsep ekonomi perhatian, atau “attention economy” menemukan relevansinya. Dalam “attention economy” (Crawford 2015, Pedersen dkk. 2021), proyek-proyek politik, bai katas nama negara, non-negara, maupun mereka sebutkan juga satu istilah, yakni ‘anti-negara’ harus mampu menarik, memikat, dan mempesona populasi yang perhatiannya tersebar di berbagai platform yang saling bersaing. Mengutip Narges Bajoghli dalam Annual Review of Anhtropology (vol.52, 2023), dalam konteks ini, “….political projects—state, nonstate, and antistate—must now beckon, seduce, and otherwise enthrall populations whose attention is spread across multiple competing platforms” (Bajoghli, 2023). Karena alasan inilah, dalam studinya, Bajoghli (2023) menggambarkan beberapa cara bagaimana ranah media, gerakan sosial, dan kekuasaan hegemonik melalui negara dan perusahaan teknologi korporat saling terkait erat, serta menyerukan lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi keterkaitan tersebut.
Saat ini, dalam dunia kita yang dijejali layer setiap harinya, politik berubah menjadi perebutan emosi publik. Visual Affan yang tergeletak di jalan dan visual joget para pejabat tak lagi sekadar dokumentasi, melainkan bahan bakar solidaritas kolektif. Konsep “attention economy” itu memberi penekanan bahwa di era banjir informasi, politik dan gerakan sosial harus berebut perhatian publik yang terbatas. Visualitas seperti foto, video, dan simbol kemudian menjelma menjadi senjata untuk menggugah emosi dan solidaritas. Negara berusaha mengalihkan perhatian dari narasi kritis, sementara gerakan sosial berjuang agar ketidakadilan terlihat, viral, dan memicu aksi kolektif. Singkatnya, politik kini adalah perebutan layar dan imajinasi publik.
Baik Nepal maupun Indonesia memperlihatkan pola yang sama. Negara mencoba menekan, yakni Nepal lewat pemblokiran media sosial, Indonesia lewat narasi elite politik yang sempat meremehkan protes. Namun visualitas rakyat menemukan jalannya. Kamera di genggaman anak muda lebih kuat daripada tembok propaganda. Bajoghli (2023) mengingatkan kita satu hal penting, bahwa visualitas tidak pernah netral. Visualitas perlu terus dibaca melalui struktur kekuasaan, yakni siapa yang dianggap korban, siapa yang dilabeli pengacau. Tetapi di tengah dominasi negara dan korporasi digital, rakyat menunjukkan bahwa mereka pun mampu menciptakan counter-narratives mengandalkan ‘senjata’ yang mereka punya, ‘senjata kaum lemah’, yakni media sosial.
Dari peristiwa di atas, ada beberapa pelajaran sederhana, namun penting bagi Indonesia. Pertama, jangan pernah meremehkan simbol kecil. Satu kebijakan, satu gestur pejabat, bisa jadi percikan api. Kedua, politik kemewahan harus dihentikan. Pamer gaya hidup atau flexing, hanya memperlebar jurang disparitas antara ‘yang berpunya’ dan ‘yang tidak berpunya’ alias wong cilik—istilah yang entah kenapa agak jarang kita dengar lagi beberapa tahun terakhir. Ketiga, dialog menjadi sesuatu lebih berharga daripada represi, karena represi hanya melahirkan luka baru. Dan yang tak kalah penting, libatkan generasi muda sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek kebijakan.
Dari kasus ‘Nepal membara’ dan demonstrasi di Indonesia beberapa waktu lalu, membuktikan bahwa rakyat—termasuk anak muda—kini tak lagi pasif. Mereka punya kamera, punya platform, dan punya bahasa visual yang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan penguasa. Pertanyaannya tinggal satu: apakah negara siap mendengar suara rakyat yang kini berbicara lewat layar, atau tetap memilih menutup mata. Anak muda pada akhirnya tidak bisa lagi sekadar menjadi pelengkap, tapi mereka harus mendapatkan sarana untuk mengekspresikan pemikirannya demi kemajuan bangsanya.
Yanuardi Syukur
Dosen Antropologi Sosial, Universitas Khairun


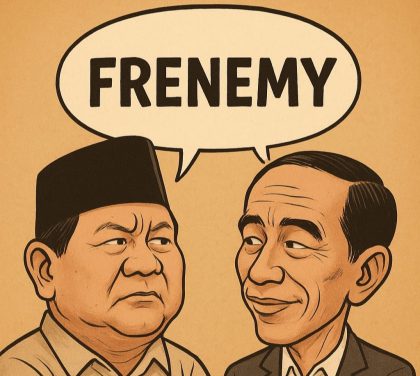




















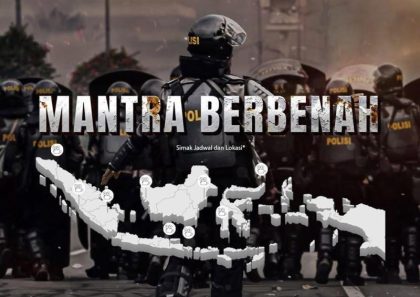








Komentar