PAI yang Terpinggirkan
Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU) selama ini masih diperlakukan sebatas Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK). Posisi ini membuat PAI sering hanya dipandang pelengkap, formalitas yang harus ada dalam kurikulum, tanpa benar-benar diberi tempat strategis dalam pengembangan keilmuan. Padahal, fungsi PAI jauh lebih besar: menyiapkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beretika, dan punya kompas moral yang jelas. Tanpa ruang kelembagaan yang kokoh, peran itu pelan-pelan tereduksi.
Fenomena yang mencolok saat ini adalah banyak PTU yang sembarangan merekrut dosen PAI. Tidak sedikit dosen PAI diisi oleh siapa saja yang dianggap “cukup mampu” mengajar, meski latar belakang keilmuannya bukan atau tidak terkait dengan bidang keagamaan. Bahkan ada kampus yang memperlakukan kuliah PAI layaknya pengajian majelis taklim: hanya berupa ceramah, tanpa pendekatan akademik dan metodologi ilmiah. Situasi ini jelas merugikan mahasiswa, karena mereka tidak mendapatkan pengalaman belajar agama yang kritis, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman.
Model pengelolaan PAI yang asal-asalan itu melahirkan dampak serius. Mutu akademik lulusan menjadi tidak seragam, bahkan menurun. Mahasiswa sering hanya memperoleh pemahaman agama yang normatif, bukan analisis kritis yang mendorong kedewasaan berpikir. Padahal, kampus semestinya menjadi ruang untuk membangun kapasitas berpikir komprehensif, bukan sekadar tempat pengulangan ceramah yang bisa mereka dapatkan di luar. Ini menjadikan PAI kehilangan daya saing sebagai bidang ilmu yang sejajar dengan disiplin lain.
Otoritas yang Luruh dan Bahaya Radikalisasi
Tidak adanya standar yang jelas juga melemahkan otoritas dosen PAI. Banyak di antara mereka yang ditempatkan di home base prodi non-agama, sehingga orientasi penelitian dan publikasinya bergeser. Dosen PAI yang seharusnya memperdalam keilmuan Islam justru sibuk mengikuti agenda akademik bidang lain. Akibatnya, otoritas keilmuan mereka luruh, kapasitasnya luntur, dan yang lebih mengkhawatirkan: sebagian menjadi rentan terseret pada narasi radikal yang tumbuh subur di luar jalur akademik resmi.
Kekosongan ruang akademik inilah yang sering diisi oleh kelompok-kelompok intoleran. Mahasiswa yang tidak memperoleh kajian agama yang sehat dan kritis di kelas PAI akhirnya mencari alternatif lain. Sumber yang mereka temui di luar kampus seringkali berisi tafsir sempit, bahkan ekstrem. Jika kondisi ini terus dibiarkan, PTU bisa menjadi ladang subur bagi radikalisasi. Ironisnya, kampus yang semestinya menjadi benteng intelektual justru berubah menjadi pintu masuk ideologi yang membahayakan.
Karir Akademik dan Urgensi Prodi Keagamaan
Masalah lain adalah karir akademik dosen PAI yang kerap terhambat. Karena tidak memiliki prodi khusus, jalur konsolidasi akademik mereka buntu. Ditambah dengan aturan jabatan fungsional yang membatasi jumlah guru besar dalam satu cabang ilmu, banyak dosen PAI akhirnya terhenti di level menengah. Mereka sulit naik pangkat meski produktif menulis. Hal ini membuat motivasi dosen menurun, riset keagamaan jarang lahir, dan regenerasi akademik terhambat. PAI akhirnya semakin terpinggirkan dari peta akademik nasional.
Dalam konteks inilah, pembukaan prodi keagamaan di PTU menjadi kebutuhan strategis. Prodi bukan sekadar struktur administratif, tetapi rumah akademik yang memulihkan otoritas dosen PAI. Dengan adanya prodi, dosen memiliki ruang untuk meneliti, menulis, dan mengajar sesuai bidangnya. Mahasiswa pun bisa menikmati perkuliahan yang lebih kaya, kritis, dan berbobot. Prodi juga memberi wadah konsolidasi, sehingga dosen tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi dalam pengembangan ilmu.
Lebih jauh, prodi keagamaan di PTU harus diarahkan pada bidang-bidang yang relate dengan dunia kerja. Misalnya, Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencetak guru sekolah umum yang kompeten secara pedagogis dan digital; Prodi Manajemen Zakat, Infaq, Wakaf, dan Filantropi Islam (ZIZWAF) untuk menghasilkan profesional di lembaga zakat dan industri keuangan syariah. Contoh lain adalah Prodi Komunikasi Islam, yang bisa mencetak content creator moderasi beragama, public speaker, dan praktisi media. Ada pula Prodi Lektur Keagamaan yang menyiapkan pakar manuskrip Islam dengan keterampilan filologi dan digitalisasi teks klasik. Tak kalah penting, Prodi Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Religi yang menyiapkan tenaga profesional di sektor perjalanan ibadah dan wisata halal. Semua itu bukan wacana, melainkan jawaban konkret terhadap kebutuhan pasar kerja.
Peran Strategis PTU
Dengan membuka prodi-prodi semacam itu, PTU bisa menunjukkan peran barunya: bukan hanya memproduksi lulusan dengan keahlian teknis, tetapi juga menghadirkan keilmuan agama yang kontekstual dan aplikatif. Ini membedakan prodi di PTU dengan prodi sejenis di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Jika PTKIN menekankan penguasaan turats, tafsir, hadis, dan fikih secara klasik, maka prodi di PTU lebih menekankan aspek aplikatif, interdisipliner, dan terhubung langsung dengan dunia kerja.
Perbedaan itu penting agar PTU tidak dianggap menduplikasi PTKIN. Sebaliknya, PTU justru melengkapi. PTKIN fokus menjaga khazanah klasik, sementara PTU menghadirkan inovasi baru yang menjawab kebutuhan kontemporer. Kombinasi keduanya akan memperkaya pendidikan tinggi kita: PTKIN menjadi penjaga tradisi, PTU menjadi jembatan ke masa depan. Sinergi inilah yang akan membuat ilmu agama tidak terjebak dalam ruang sempit, tetapi hadir di ruang publik sebagai solusi nyata.
Lebih dari sekadar menyiapkan lulusan siap kerja, PTU juga punya mandat moral untuk ikut membangun kultur beragama yang sehat di lingkungan akademik. PTU harus mampu menumbuhkan nalar beragama yang kritis, terbuka, lintas disiplin, dan universal. Dengan begitu, agama tidak berhenti sebagai doktrin normatif, melainkan hadir sebagai inspirasi etis dalam sains, teknologi, ekonomi, maupun kebudayaan. Inilah kekhasan PTU: menghadirkan corak keberagamaan yang lebih dialogis, inklusif, dan sejalan dengan tantangan global.
Kehadiran prodi keagamaan di PTU juga akan memperkuat moderasi beragama. Mahasiswa tidak lagi terpapar kuliah PAI yang dangkal atau radikal, melainkan diskursus akademik yang sehat. Dosen PAI pun kembali berwibawa karena didukung riset dan publikasi. Dengan demikian, kampus umum bisa berfungsi sebagai benteng kebangsaan: mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan kokoh dalam komitmen kebangsaan.
Tentu, pembukaan prodi baru membutuhkan keberanian politik kebijakan. Kemenag, Kemendikbudristek, dan pihak kampus harus duduk bersama. Tidak boleh lagi ada tarik-menarik kewenangan yang membuat dosen PAI terlunta-lunta. Pemerintah harus berani memberi mandat, standar, dan dukungan agar prodi keagamaan di PTU bisa lahir dan berkembang. Tanpa itu, keluhan tentang dosen yang stagnan, kuliah PAI yang dangkal, dan mahasiswa yang rentan radikalisasi akan terus berulang.
Lebih jauh, alumni bidang keagamaan dari PTU diharapkan bisa menjadi mitra sejajar alumni PTKIN dalam ber-fastabiqul khairat. Keduanya dapat saling melengkapi, bahu-membahu, dan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang relevan, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, kesetaraan gender, hingga penguatan perdamaian dan keadilan. Dengan sinergi itu, ilmu agama tidak hanya berhenti di ruang kelas, melainkan benar-benar memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan global.
Singkatnya, prodi keagamaan di PTU adalah investasi masa depan. Ia memberi tempat terhormat bagi dosen, memberi ruang belajar sehat bagi mahasiswa, dan memberi jawaban nyata atas kebutuhan bangsa. Kita tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa PAI di kampus umum sedang kehilangan arah. Menjadikan kuliah agama sekadar “pengajian kampus” adalah pengkhianatan terhadap semangat akademik. Inilah saatnya PTU bangkit: menghadirkan prodi keagamaan yang serius, kritis, dan relate dengan dunia kerja. Karena bangsa ini butuh generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga bermoral dan berkarakter.
Andy Hadiyanto
Dosen PAI UNJ, Ketua Umum DPP ADPISI













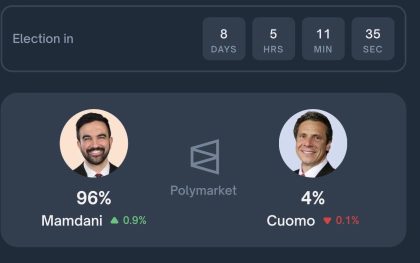


















Komentar