Sekitar tahun 1992, Prof. Dr. Mukti Ali, ketika berada di sela-sela sebuah seminar di Gontor, tiba-tiba berkata, “Bagi saya Islamisasi ilmu pengetahuan itu omong kosong, apa yang hendak diislamkan, ilmu itu kan neutral.” Prof. Dr. Baiquni, yang ketika itu berada bersamanya, segera menimpali, “Pak Mukti tidak belajar sains, jadi tidak tahu di mana letaknya ilmu (sains) itu tidak Islam.”
Dengan penuh minat, Pak Mukti bertanya, “Masakan begitu, bagaimana itu?” Baiquni menjawab, “Sains di Barat itu, pada tahap asumsi dan pra-anggapan (presuppositions)-nya, tidak melibatkan Tuhan. Alam ini dianggap bukan ciptaan Tuhan.” “Maka daripada itu,” lanjutnya, “ilmu yang dihasilkan adalah ilmu yang sekular dan bahkan anti-Tuhan.” Dengan kejujuran intelektual dan sikap akademiknya, Pak Mukti spontan menjawab, “Oh, begitu.” Perbincangan pun berlanjut, dan persoalan tentang ilmu serta Islamisasinya menjadi topik yang menarik.
Benarkah ilmu pengetahuan moden hari ini tidak mengakui adanya Tuhan? Pernyataan Prof. Baiquni itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R. Hooykaas dalam Religion and The Rise of Modern Science.
Di Barat, dunia pada asalnya digambarkan sebagai suatu organisme, namun sejak munculnya Copernicus hingga Newton, pandangan itu bergeser menjadi mekanistik. Pergeseran pandangan ini pada abad ke-17 telah diprotes oleh para pengikut Aristotle. Menurut mereka, pandangan terhadap dunia yang mekanistik itu telah menggiring manusia kepada ateisme (kekufuran).
Namun, para pendukung faham mekanisme seperti Beeckman, Basso, Gassendi dan Boyle tidak bersetuju. Dengan berpegang kepada konsep mukjizat, Boyle, misalnya, beralasan bahawa gambaran mekanistik juga boleh bersifat religius. Jika unsur materi dan gerakan yang menjadi inti kepada organisme tidak cukup untuk menjelaskan fenomena alam, maka ini menunjukkan adanya kemungkinan intervensi Tuhan melalui mukjizat.
Ini bererti masih ada peranan Tuhan di situ — Tuhan boleh, pada bila-bila masa, turun tangan mempengaruhi kausalitas alam semesta. Inilah yang disebut sebagai occasionalisme, yang menjadi doktrin teologi Kristian hingga kini. Maksudnya, Tuhan sangat transenden, berada jauh di sana dan tidak terjangkau, sedangkan alam berada di sini dan tidak sentiasa di bawah pengawasan Tuhan.
Menggambarkan dunia sebagai sebuah mekanisme bermakna melihatnya sebagai mesin. Bagi yang ateis, mesin itu wujud dengan sendirinya. Bagi yang beriman, mesin itu diciptakan. Namun di Barat, kekuasaan Sang Pencipta itu lama-kelamaan direduksi dan akhirnya dihapuskan. Dunia dahulu diciptakan, tetapi kini dianggap bebas daripada Penciptanya.
Belum lama setelah Henri de Monantheuil, seorang penulis Perancis, pada tahun 1599 menyatakan bahawa Tuhan ialah pencipta mesin dan ciptaan-Nya — iaitu dunia ini — berjalan seperti sebuah mesin, masyarakat gereja menjadi berang. Tuhan gereja dianggap tidak lagi terlibat dalam urusan dunia.
Fahaman mekanistik tentang dunia inilah yang kemudian menguasai cara fikir Barat moden. Paradigma positivisme dan empirisisme dalam sains Barat berkembang subur. Otoriti untuk memahami dunia berpindah daripada gereja kepada tangan saintis.
Descartes, Gassendi, Pascal, Berkeley, Boyle, Huygens dan Newton — yang kononnya membela Tuhan — akhirnya merebut otoriti Tuhan itu sendiri. Kesombongan para pemikir Yunani diulang semula melalui semboyan “Man is the standard of everything” (Manusia ialah ukuran segala sesuatu). Benar-salah, baik-buruk, tidak lagi memerlukan campur tangan Tuhan. Wahyu dikalahkan, atau digantikan, oleh akal.
Jika dahulu gereja boleh memarahi Copernicus dan Galileo serta menghukum mati Bruno, kini gereja hanya dapat menangisi ulah para saintis. Sementara itu, para saintis bersikap acuh dan berkata, “Apa yang tidak dapat dibuktikan secara empiris bukanlah sains.”
Teologi tidak boleh masuk ke dalam ranah sains. Bicara tentang fizik tidak perlu melibatkan metafizik. Francis Bacon, dengan argumentasi yang sangat empiris, berkata: “Ilmu berkembang kerana adanya persamaan-persamaan, sedangkan Tuhan tidak mempunyai persamaan.” Oleh sebab itu, dalam teorinya tentang idola, Bacon menegaskan agar tidak melakukan induksi berdasarkan keyakinan.
Selain itu, Bacon juga mengakui bahawa manusia sebenarnya jahil tentang kehendak dan kekuasaan Tuhan yang tersurat dalam wahyu dan tersirat dalam ciptaan-Nya. Descartes pun berpendapat bahawa kehendak Tuhan tidak dapat difahami, sehingga hal itu menghalang jalan rasionalisme. Maka katanya, “Kita tidak perlu takut melawan wahyu Tuhan dan dilarang meneliti alam ini,” kerana tidak ada larangan dalam wahyu. Tuhan memberi manusia hak untuk menguasai alam. Oleh sebab itu, manusia boleh menjadi seperti Tuhan dan mengikuti petunjuk akalnya.
Jadi, sebenarnya para saintis bukan tidak mempercayai Tuhan, tetapi mereka sukar menghubungkan teologi dengan epistemologi. Akibatnya, standard kebenaran dan kaedah penyelidikan akhirnya dimonopoli oleh empirisisme rasional.
Sebenarnya, argumentasi Descartes dan Bacon masih belum jauh beranjak daripada persoalan yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd terhadap al-Ghazali. Namun kerana Ibn Rusyd lebih popular di kalangan gereja dengan faham Averoisme-nya, pemikiran al-Ghazali tidak diambil kira.
E. Gilson, dalam karyanya Revelation and Reason, dengan jelas menyalahkan Ibn Rusyd. Menurutnya, dengan teori kebenaran ganda, Ibn Rusyd dianggap telah menabur benih sekularisme yang kemudian mempengaruhi Descartes, Malebranche, David Hume dan para pemikir Barat lainnya.
Tuhan tetap disembah dan diakui kewujudan-Nya, tetapi tidak lagi ditemui hubungannya dengan akal, ilmu, atau sains. Padahal, bagi al-Ghazali, kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan rasio manusia. Kehendak Tuhan dalam realiti alam ini dapat difahami secara rasional melalui satu istilah — sunnatullah.
Syed Muhammad Naquib al-Attas segera menyedari bahawa ilmu pengetahuan moden ternyata sarat dengan nilai-nilai Barat. Ia berlandaskan akal semata-mata dan berpaksikan pandangan dunia yang dualistik. Realiti dibatasi hanya pada kewujudan yang bersifat temporal, sementara manusia dijadikan pusat segalanya.
Ismail al-Faruqi dan Seyyed Hossein Nasr turut mengakui hal ini. Al-Faruqi menyoroti masalah dualisme ilmu dan sistem pendidikan umat Islam, manakala Nasr mengkritik penghapusan jejak Tuhan daripada hukum alam dan realiti kosmos. Ketiga-tiga tokoh ini seakan menyesali keadaan dunia moden — seandainya bukan Barat yang menguasai dunia, eksploitasi alam yang merosakkan itu tidak akan terjadi.
Ilmu seperti itulah yang perlu diislamkan, kata al-Attas. Namun, mengislamkan ilmu bukanlah dengan mengucapkan syahadah atau berjabat tangan dengan qadi. Mengislamkan ilmu bermakna membebaskannya, menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Membebaskannya daripada fahaman sekular yang menguasai fikiran umat Islam — khususnya dalam menafsirkan fakta-fakta dan merumuskan teori-teori.
Pada saat yang sama, ilmu itu perlu diisi dengan konsep din, manusia (insan), ilmu (ʿilm dan maʿrifah), keadilan (ʿadl), serta konsep amal yang benar (amal sebagai adab), dan sebagainya.
Jika Thomas Kuhn menegaskan bahawa ilmu itu sarat nilai, dan paradigma keilmuan harus diubah berdasarkan worldview masing-masing saintis, maka bagi seorang Muslim yang cerdas tentu akan bergumam, lā siyyamā — apatah lagi bagi seorang Muslim.
Lalu, apakah setelah itu akan lahir mobil Islam, mesin Islam, pesawat terbang Islam dan sebagainya? This is a silly question, kata al-Attas suatu ketika. Yang diislamkan bukanlah objek ilmu (al-ma‘lūm), bukan pula teknologinya, tetapi ilmu dalam diri al-ʿālim (subjek yang mengetahui). Yang diislamkan ialah paradigma saintifik dan sekaligus pandangan dunianya (worldview).
Apabila paradigma dan pandangan dunia itu telah tunduk dan berserah diri kepada Tuhan, maka sains akan mampu menghasilkan teknologi yang ramah terhadap alam. Teknologi seperti itu akan sejalan dengan maqāṣid al-sharīʿah, bukan dengan nafsu manusia.
Dengan pandangan dunia Islam, akan lahir ilmu yang sesuai dengan fitrah manusia, fitrah alam semesta, dan fitrah yang diturunkan (fitrah munazzalah), iaitu al-Qur’an — meminjam istilah Ibn Taymiyyah. Dengan paradigma keilmuan Islam, akan muncul ilmu yang memadukan ayat-ayat Qur’aniyyah, Kauniyyah, dan Nafsiyyah.
Hasilnya ialah ʿilm al-nāfiʿ, ilmu yang bermanfaat — yang menjadi nutrisi iman dan pemangkin amal. Itulah miṣykāt (cahaya) yang menerangi kegelapan akal dan kekeliruan pemikiran.
Prof. Hamid Fahmy Zarkasyi


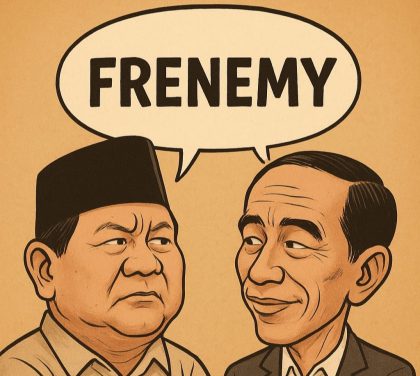




















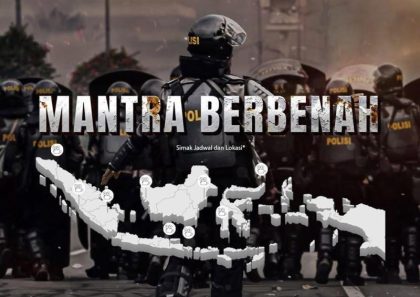








Komentar