Apa jadinya muslim tanpa sastra? Dalam arti tidak membaca karya sastra, memahaminya, apalagi mempraktikan pesan-pesan kesusastraan dalam keseharian. Saya mengajukan pertanyaan demikian pada diri sendiri. Jawaban sementara, saya memandang sekelebatan, mereka tetap bisa hidup, menjalani kehidupan dengan normal. Bisa hidup berkecukupan, bahkan bisa menjadi kaya tanpa harus membaca karya sastra. Singkat cerita, bisa hidup bahagia tanpa sastra. Lantas, apa gunanya sastra?
Sebenarnya, ini pertanyaan eksistensial pada diri pribadi saya pada mulanya. Sekian lama saya tenggelam dalam dunia sastra. Memang, saya tak menulis, tepatnya belum punya minat untuk menulis karya sastra yang diterbitkan secara serius menjadi buku. Saya hanya sekadar membaca karya sastra (novel, cerpen atau buku kumpulan puisi) dari beragam penulis dan sastrawan. Saya lantas bertanya, apa gunanya saya menghabiskan waktu selama ini untuk membaca buku-buku sastra semacam itu?
Saya mulai berpikir, apakah ini sia-sia belaka? Saya teringat surat Asy-Syu’ara” (penyair) dalam Al-Quran. Pada ayat-ayat awal, memang dikisahkan bagaimana laknatan kepada penyair yang disebutkan berjalan “dari lembah ke lembah” diikuti oleh orang-orang sesat. Atas dasar kisah ini, lantas ada beberapa orang yang saya dengar berpendapat bahwa Islam tidak memberi ruang bagi (penulisan) sastra. Apakah benar demikian?
Kalau kita cermati tentang ayat-ayat laknatan pada ayat-ayat awalan, selanjutnya menyelami ayat penutupan, maka kita bakal mendapatkan kearifan dan kejernihan pemahaman tentang peran penting seorang penyair, lebih umunya sastrawan dalam Islam. Sementara itu, kalau kita mau menjelajah konteks sejarah, rasa-rasanya juga tak bakal semena-mena (lagi) menghakimi karya sastra atau lazimnya dikenal sebagai fiksi dalam tradisi kepengarangan saat ini.
Dulu syair, oleh penyair digunakan sebagai media komunikasi para juru bicara kabilah. Syair-syair yang dituliskan berisikan kehidupan sekitar kabilah seperti peperangannya dengan kabilah lain. Permusuhan antar kabilah menjadi inspirasi para penyair. Pembelaan terhadap kabilahnya sendiri tentu mengilhami penyair menuliskan sajaknya. Tak hanya membela kabilahnya sendiri, konon syair-syair Arab tempo dulu juga tak jarang berisi cemoohan, hinaan, ejekan pada kabilah lain.
Sajak lain yang tercipta, ungkapan cinta penyair pada gadis-gadis cantik yang dikenalnya pada lingkungan kabilahnya. Konon, dulu sajak yang juga digemari, ialah sajak cinta birahi yang tak jarang penuh muatan pornografi. Begitu juga sajak yang dikenal dengan istilah sajak “Khamiriyyah”, pemujaan berlebihan pada arak atau anggur. Seringkali, keindahan gelas dan anggur beserta rasa nikmatnya diumpamakan atau disamakan dengan kecantikan gadis dan kenikmatan yang diperoleh dari mencintainya.
Al-Quran, menolak penyair-penyair semacam ini.
Islam datang, memberi warna baru. Tradisi lama penciptaan sajak membekali bangsa Arab (Islam) kemudian mencintai dan melahirkan karya-karya bermutu tinggi. Bukan lagi melulu soal kemolekan gadis cantik, juga bukan kesukuan yang sempit. Sajak-sajak lebih banyak berisi puji-pujian. Terutama ditujukan pada pribadi Rasulullah. Ia kemudian melahirkan genre yang disebut “Al-mada’ih Al-Nabawiyah” atau “Na’tiyah” (pujian) dalam bahasa Persia. Puji-pujian juga ditujukan pada kepahlawanan membela risalah agama yang benar, membela kaum teraniaya (tertindas) serta menegakkan kemanusiaan dalam arti luas.
Perkembangan sastra awal. Pada zaman Islam, sesuai dengan perkembangan masyarakat madani yang dibangun Nabi di Madinah setelah hijrah, penulisan karya sastra mulai berkembang. Diantara pelopornya adalah Ali ibn Abi Thalib, yang khotbah-khotbah dan wejangan-wejangannya dituturkan dalam bahasa sastra yang indah dan konon dihimpun dalam kitab bermutu sastra “Nahj Al-Balaghah”. Beliau juga bisa dikatakan sebagai penulisan sajak bernafaskan Islam.
Kedudukan sastra yang diberi penghargaan tinggi dalam Islam, bisa ditelisik dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, “Sebaik-baik penyair ialah Labid yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu lenyap selain Allah SWT.” Kecintaan masyarakat muslim kepada sastra juga berkaitan dengan kegairahan mengkaji bahasa dan nilai sastra Al-Quran.
Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi (Surat Al-Alaq) dimulai dengan seruan “Baca” (Iqra), yaitu menyimak wacana dengan pemahaman yang mendalam sehingga lahir pengetahuan dan wawasan budaya yang luas, juga mendorong perkembangan baca tulis. Karena itu pula, Al-Quran memandang tinggi hasil tulisan kalam (pena).
Cerita sastra Islam demikian, kalau diteruskan tentu teramat panjang.
Kembali kepada pertanyaan di atas. Seorang muslim, bisa hidup tanpa sastra. Tapi, ketika sastra menjadi bagian dari kehidupannya, bisa memberikan warna tersendiri baginya, tak lain tak bukan estetika melekat dalam dirinya. Kalau kita perhatikan, melekatnya unsur-unsur estetik dalam penyampaian ayat-ayat Al-Quran, membuktikan bahwa risalah Islam mengakui bagaimana estetika, sebagaimana metafisika, logika, epistemologi merupakan bagian dari kehidupan manusia.
Dengan demikian, ketika seorang muslim mengakrabi sastra, ia bakal merasakan bagaimana estetika menemukan warnanya. Sementara, estetika dalam Islam sendiri adalah konsep keindahan yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seni, arsitektur, dan perilaku sehari-hari. Estetika Islam menekankan pada keindahan yang selaras dengan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitulah sastra (Islam), seorang muslim yang bersastra menemukan urgensinya. []
Yons Achmad. Kolumnis. Tinggal di Depok.


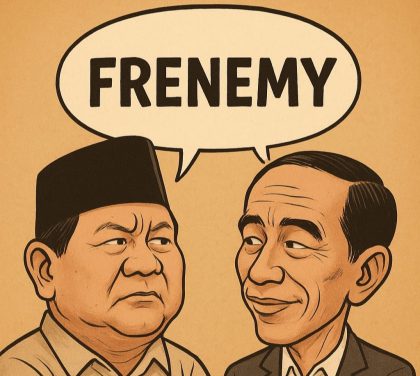




















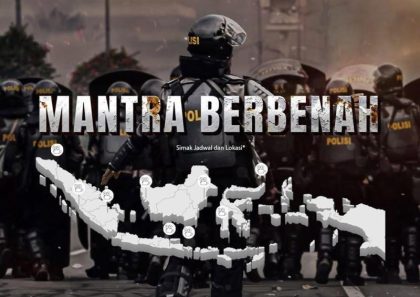








Komentar