Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pernyataan yang membuat publik terperangah. Ia menyebut bahwa praktik pungutan liar sudah merembes ke hampir semua lini organisasi kepolisian. “Dari urusan naik pangkat, pindah jabatan, sampai penempatan tugas, ada laporan bahwa semua itu bisa diatur dengan bayar,” ujarnya. Pernyataan ini bukan sekadar kritik, tetapi alarm akan kerusakan sistemik.
Temuan Komisi Reformasi Polri menunjukkan bahwa pungli bukan lagi perilaku individu yang menyimpang, tetapi telah berubah menjadi budaya kerja. Ketika budaya membusuk, individu yang baik pun ikut terseret. Laporan internal bahkan menyebutkan bahwa mekanisme pengawasan seperti Propam tidak berjalan optimal dan kerap tumpul ke dalam. Kombinasi ini—budaya rusak dan pengawasan lemah—adalah formula sempurna bagi berkembangnya penyimpangan kekuasaan.
Menurut pakar tata kelola pemerintahan, Prof. Agus Pramusinto, aparat bersenjata yang tidak dibentengi moral adalah ancaman bagi keamanan negara. “Masalah Polri bukan hanya soal pungli, tetapi dekadensi akhlak. Ketika nilai moral luntur, setiap instrumen kekuasaan berubah menjadi alat pemerasan,” tegasnya. Hal ini menjelaskan mengapa kasus-kasus pelanggaran etik di tubuh Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketika Kekuasaan Tanpa Moral Menjadi Mesin Penyalahgunaan
Dalam teori kepemimpinan, John C. Maxwell mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moralitas selalu menuju penyimpangan. Dalam konteks Polri, penyimpangan itu bisa muncul dalam bentuk:
* kriminalisasi terhadap warga,
* penyalahgunaan kewenangan penahanan,
* rekayasa kasus,
* pemerasan terhadap masyarakat,
* atau perlindungan terhadap aktivitas ilegal.
Negara memberikan kewenangan luar biasa kepada Polri: menahan, menggeledah, menyita, bahkan menggunakan senjata mematikan. Tanpa kontrol akhlak, kewenangan itu dapat berubah menjadi alat represi.
Kasus Ferdy Sambo misalnya, membuka mata publik bahwa penyalahgunaan wewenang dapat bertingkat dari level individu hingga struktural. “Sambo bukan kasus tunggal. Ia hanya puncak gunung es dari budaya kekuasaan yang tidak dikawal moral,” kata pakar etik pemerintahan, Yudi Latif.
Retaknya Citra Publik dan Jejak Pelanggaran yang Viral
Pakar komunikasi digital, Dr. Rulli Nasrullah, menilai bahwa tantangan Polri kini bukan hanya soal integritas, tetapi transparansi digital. “Kesalahan kecil polisi kini bisa menjadi krisis nasional dalam hitungan menit,” ujarnya. Perilaku arogan di lapangan, kekerasan berlebih saat razia, hingga video polisi mengutip uang warga menjadi viral dan meruntuhkan kepercayaan publik.
Dalam survei Indikator Politik Indonesia (2024), kepercayaan publik pada Polri naik-turun secara ekstrem setiap kali mencuat kasus besar. Artinya, citra Polri sangat bergantung pada akhlak anggotanya, bukan hanya pada kinerja formal.
Di Ruang Pendidikan, Akhlak Masih Sekadar Formalitas
Di lingkungan pendidikan Polri, pelajaran etika dan pembinaan mental memang sudah ada. Namun sejumlah laporan internal menunjukkan bahwa materi etika masih dianggap pelengkap, bukan pondasi. Fokus utama tetap pada fisik, taktik, dan penegakan hukum. Padahal negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris menempatkan moralitas sebagai inti pendidikan kepolisian.
Menurut mantan Komisaris Polisi Inggris, Sir Robert Peel, “The police are the public and the public are the police.” Artinya polisi bukan kekuatan yang berada di atas masyarakat, tetapi bagian dari masyarakat. Prinsip ini hilang ketika akhlak tidak menjadi prioritas.
Ketika Pengawasan Tumpul, Budaya Buruk Beranak-Pinak
Komisi Reformasi Polri menemukan bahwa Propam tidak memiliki independensi yang cukup untuk mengawasi pelanggaran etik. Banyak laporan pelanggaran justru ditangani oleh pejabat yang juga memiliki kepentingan.
Menurut pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita, masalah Polri bersifat struktural. “Pengawasan internal tidak boleh dipimpin oleh orang yang memiliki kedekatan struktural dengan pelanggar. Tanpa jarak, pengawasan menjadi formalitas.” Pernyataan ini menjelaskan mengapa banyak kasus pelanggaran diproses setengah hati atau menguap begitu saja.
Untuk memperbaiki kondisi Polri, pendidikan akhlak tidak boleh lagi menjadi hiasan kurikulum, melainkan strategi nasional. Reformasi akhlak Polri harus dilakukan melalui:
1. Integrasi pelatihan akhlak sejak pendidikan dasar kepolisian
Bukan hanya penguatan mental, tetapi pendidikan karakter sistematis yang mengakar pada nilai kejujuran, empati, dan anti-korupsi.
2. Keteladanan moral dari pimpinan
Etika hanya efektif bila dipraktikkan pemimpin. Tanpa contoh dari atas, instruksi moral tidak akan digubris.
3. Pengawasan internal yang independen
Propam harus diperkuat dengan mekanisme audit moral, evaluasi berjenjang, dan pengawasan terbuka.
4. Lingkungan kerja yang menghalangi pungli
Budaya yang mendukung integritas lebih efektif daripada sanksi, karena mencegah pelanggaran sebelum terjadi.
Khazanah Islam: Akhlak sebagai Pondasi Kekuasaan
Dalam tradisi Islam, kekuasaan tanpa akhlak disebut sebagai zulm (kezaliman). Imam Al-Ghazali mengingatkan:
“Kerusakan negara dimulai dari rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusakya ulama. Rusaknya ulama karena cinta dunia dan jabatan.”
Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal paling adil ini mengingatkan:
“Kekuasaan tidak akan baik kecuali dengan kebenaran, dan kebenaran tidak akan tegak tanpa akhlak.” Hasan Al-Bashri, seorang tabiin dan ulama besar dalam bidang akhlak berkata: “Jika rakyatmu berbuat buruk, maka lihatlah bagaimana perilaku para pemimpinnya; sesungguhnya manusia mengikuti pemimpinnya.”
Syaikh Abdul Qadir al-Jilani mengingatkan, “Tidak ada amanah yang lebih berat daripada kekuasaan. Maka jangan kau pegang kecuali dengan akhlak, karena kekuasaan tanpa akhlak akan membinasakanmu dan orang lain.”
Ibn Taymiya, salah satu ulama besar yang banyak membahas pemerintahan dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menyatakan,“Allah menolong negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menolong negara yang zalim meskipun Muslim.”
Syaikh Muhammad Abduh, dalam reformasi dunia Islam modern, ia menulis, “Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya hukum, tetapi oleh akhlak orang-orang yang menegakkan hukum itu.”
Buya Hamka, dalam bukunya Lembaga Budi mengingatkan,“Jabatan adalah ujian. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang budi pekertinya lebih tinggi daripada kekuasaannya.” Sedangkan KH. Hasyim Asy’ari dalam Adabul ‘Alim wal Muta’allim menegaskan,“Akhlak adalah mahkota. Tanpa akhlak, ilmu menjadi fitnah, dan jabatan menjadi dosa.”
Maka reformasi Polri tak boleh berhenti pada digitalisasi, SOP baru, atau restrukturisasi. Semua itu sia-sia tanpa reformasi akhlak. Budaya korup, pungli jabatan, penyalahgunaan kewenangan, hingga kekerasan berlebih adalah gejala dari satu akar masalah: akhlak aparat yang melemah. Jika Polri ingin kembali dipercaya, reformasinya harus dimulai dari dalam hati setiap anggotanya. Wallahu alimun hakim.
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik









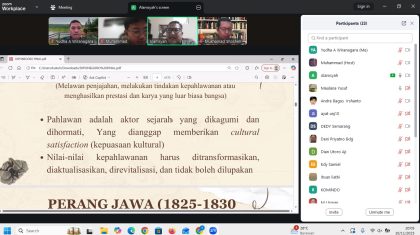




















Komentar