Mengajarkan Pemikiran Politik Barat di Indonesia
Oleh : Peter Berkowitz
Pada hari Jumat dan Sabtu, 15–16 Agustus, tepat sebelum rakyat Indonesia dengan bangga merayakan 80 tahun kemerdekaan pada Minggu, 17 Agustus, saya memimpin empat seminar berdurasi tiga jam di ibu kota tentang sejarah pemikiran politik Barat. Saat ini saya juga ikut mengajar empat seminar tambahan – tentang kenegaraan, urusan luar negeri, agama, dan hak asasi manusia – bersama rekan saya, Profesor Emerita Hukum Harvard Mary Ann Glendon, yang bergabung secara virtual dari Amerika Serikat.
Sekitar 25 peserta seminar adalah anggota Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim independen terbesar di dunia dengan sekitar 150 juta pengikut, yang berkantor pusat di Jakarta. Kelompok kecil ini terdiri dari tokoh-tokoh senior NU – sebagian besar laki-laki, tetapi tidak sepenuhnya – yang berprofesi sebagai profesor universitas, kolumnis surat kabar, pimpinan pesantren NU, dan lainnya. Salah satu pesertanya adalah seorang perempuan yang memimpin organisasi perempuan NU dengan anggota 36 juta orang. Pada akhir Juni, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) yang baru didirikan, bekerja sama dengan Center for Shared Civilizational Values berbasis di North Carolina, meluncurkan Kursus Dasar enam bulan yang mengadakan seminar hampir setiap akhir pekan hingga Desember.
Upaya pendidikan ambisius NU ini lahir dari Islam Nusantara, aliran Islam toleran dan pluralis yang berkembang di Indonesia selama lebih dari 700 tahun. Sesuai keyakinan agama mereka, para peserta seminar menyambut baik pertemuan dengan tulisan klasik pemikiran politik Barat, baik kuno maupun modern, dan terinspirasi untuk mengajukan pertanyaan tajam tentang kebebasan dan demokrasi di Barat, Indonesia, dan dunia.
Didirikan pada 1926, NU memadukan pengabdian religius dengan keterlibatan politik. Pada 1940-an, NU mendukung kemerdekaan Indonesia; pada 1960-an, NU berperan penting dalam mengalahkan komunisme di Indonesia; dan pada 1990-an, NU mendukung transisi demokrasi bangsa. Saat ini, NU mempromosikan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia yang setara, baik di dalam Islam, di seluruh Indonesia, maupun di antara bangsa-bangsa lain.
AKN-NU memperkuat misi NU dengan menyediakan pendidikan luas yang memadukan keunggulan Islam dan Barat. Pendidikan ini diyakini NU selaras dengan ajaran Islam, mempererat pemahaman lintas iman dan dialog antarperadaban, serta membentuk cendekiawan, jurnalis, pendidik, penggerak, dan pejabat pemerintah yang mampu memperkuat demokrasi Indonesia yang melindungi hak, multiagama, dan multietnis.
Indonesia, yang menjadi sasaran operasi pengaruh Partai Komunis Tiongkok, seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari diplomasi Amerika. Sebagai republik presidensial, Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kedelapan terbesar di dunia. Dengan sekitar 285 juta penduduk, Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, serta negara terpadat keempat setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Muslim Indonesia berjumlah sekitar 240 juta – terbanyak dibanding negara manapun. Indonesia juga memiliki hampir 30 juta umat Kristen, hampir 5 juta umat Hindu, dan lebih dari 300 kelompok etnis. Penduduknya menuturkan lebih dari 700 bahasa. Indonesia meraih skor tertinggi dalam Global Flourishing Study April 2025. Semboyannya adalah “Bhinneka Tunggal Ika”. Konstitusinya menegaskan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum serta menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, berkumpul, berasosiasi, dan berekspresi. Terbentang di garis khatulistiwa sepanjang lebih dari 3.000 mil dengan sekitar 17.000 pulau, Indonesia menempati posisi strategis di jalur laut Indo-Pasifik.
NU juga patut diperhatikan Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS, bukan hanya karena kiprahnya di Indonesia. Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengecam bangkitnya ekstremisme Islam di Timur Tengah yang berupaya menaklukkan dengan kekerasan, menundukkan bahkan melenyapkan orang kafir, dan mendirikan kembali kekhalifahan. Dalam tulisan The Civilizational Origins of Indonesia’s Nahdlatul Ulama and its Humanitarian Islam Movement, Staquf bersama C. Holland Taylor menjelaskan bahwa NU telah memelopori “strategi global untuk mendamaikan ajaran Islam dengan realitas dunia modern yang konteks dan kondisinya berbeda jauh dari ketika hukum Islam klasik lahir.”
Rekonsiliasi Islam dan modernitas ala NU, tulis Staquf dan Taylor, membutuhkan “upaya jangka panjang, sistematis, dan institusional untuk merekontekstualisasi (mereformasi) ajaran ortodoksi Islam yang usang dan bermasalah serta cenderung melahirkan kebencian, supremasi, dan kekerasan.” Reformasi ini dilakukan dari dalam, setia pada Islam, dengan prinsip-prinsip fiqh klasik yang sama, namun untuk menjawab tantangan moral dan politik masa kini. NU berusaha “menyelaraskan ajaran Islam dengan dunia modern demokrasi dan hak asasi manusia” melalui ijtihad dalam merumuskan hukum Islam.
Pada musim panas 2020, mewakili NU, sahabat lama saya Dr. Timothy Shah menulis surat kepada saya – saat itu saya menjabat direktur Policy Planning Staff Departemen Luar Negeri AS dan sekretaris eksekutif Commission on Unalienable Rights – untuk menyampaikan apresiasi NU atas laporan terbaru komisi tersebut. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo membentuk komisi itu pada musim panas 2019 dan menunjuk Prof. Glendon sebagai ketuanya.
Di tengah kontroversi soal status dan cakupan hak asasi manusia, Pompeo meminta komisi tersebut memperkuat kembali komitmen Amerika pada hak-hak yang melekat pada manusia – “unalienable rights” dalam istilah abad ke-18, atau hak asasi manusia dalam istilah modern – yang berakar pada prinsip-prinsip pendirian bangsa, tradisi konstitusional, serta kewajiban yang Amerika terima pada 1948 ketika mendukung Universal Declaration of Human Rights. NU, yang sejak lama melihat dalam iman Islam dan tradisi Indonesia sumber moral, filosofis, dan religius bagi hak dasar dan kebebasan fundamental, menemukan semangat yang sejalan dalam laporan itu.
Kursus Dasar AKN-NU membekali anggota NU, sejalan dengan deklarasi NU 1984, agar lebih efektif mempromosikan persaudaraan – di antara sesama Muslim, warga Indonesia, dan umat manusia. Kurikulumnya mencakup lebih dari 100 kelas: sejarah NU; sejarah, seni, dan budaya Islam; tradisi politik Barat; prinsip ekonomi sejak Adam Smith; kenegaraan dan hubungan dunia; sains, teknologi, dan AI; Kekristenan, Yudaisme, Hindu; serta India, Afrika Sub-Sahara, dan Tiongkok.
Seminar saya menyajikan tinjauan pemikiran politik Barat serta memperkenalkan beberapa karya besar, gagasan inti, dan ketegangan abadi dalam tradisi tersebut.
Seminar pertama membahas era kuno: perdebatan antara kaum kuno yang menilai politik bertujuan menumbuhkan kebajikan, dan kaum modern yang menekankan politik demi kebebasan. Kami mengkaji Plato dan Aristoteles, serta upaya Muslim, Yahudi, dan Kristen Abad Pertengahan mendamaikan iman dan akal.
Seminar kedua membahas tradisi kebebasan modern, terutama John Locke dan pemikirannya tentang kebebasan alami, kesetaraan, dan toleransi.
Seminar ketiga mengulas tradisi politik Amerika melalui The Federalist Papers.
Seminar keempat mengulas kelemahan demokrasi dan kebebasan, serta cara mengatasinya dengan tetap menjaga prinsip-prinsip itu – termasuk Burke, Tocqueville, Mill, Hayek, serta kritik radikal Karl Marx. Kami juga membahas akar Marxisme dalam “wokeism” progresif dan ancamannya terhadap pemerintahan demokratis.
Diskusi kami menyingkap kesamaan yang mencolok – meski penuh perbedaan – antara Amerika Serikat dan Indonesia. Keduanya sama-sama melawan penjajahan Barat untuk meraih kemerdekaan. Amerika didirikan oleh kaum Kristen, tapi bukan sebagai republik Kristen; Indonesia didirikan oleh kaum Muslim, tapi bukan sebagai republik Islam. Dan sebagaimana umat Kristen di Amerika memberi alasan berbasis agama untuk memisahkan agama dan negara, umat Muslim di Indonesia juga melakukannya dengan alasan dari Islam.
Dalam bulan-bulan pertamanya, Kursus Dasar NU telah menunjukkan bahwa pemikiran politik Barat menyediakan landasan bersama untuk membahas isu-isu penting bagi demokrasi yang melindungi hak di seluruh dunia.
Pendidik dan diplomat Amerika sebaiknya mengambil pelajaran berharga ini. Jika kajian bersama tradisi Barat dapat mempererat pemahaman lintas samudra dan peradaban, maka di Amerika sendiri tradisi ini dapat membantu menjembatani jurang antara kanan dan kiri di kampus-kampus. Ia juga dapat meningkatkan pemahaman para diplomat AS tentang kekuatan dan kelemahan bangsa mereka serta bangsa-bangsa sahabat dan lawan. II
Peter Berkowitz adalah senior fellow di Hoover Institution, Universitas Stanford. Dari 2019 hingga 2021, ia menjabat direktur Policy Planning Staff di Departemen Luar Negeri AS. Tulisan-tulisannya ada di PeterBerkowitz.com dan ia bisa diikuti di X @BerkowitzPeter. Buku barunya berjudul Explaining Israel: The Jewish State, the Middle East, and America. Ia juga dikenal sebagai pendukung kuat Negara Zionis Yahudi Israel.
NB: Ilmuwan politik pro Israel ini beberapa hari lalu diundang Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf untuk ceramah di Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama dan Universitas Indonesia. Ketum NU itu akhirnya minta maaf ke publik setelah beredar informasi bahwa Berkowitz adalah pendukung kuat negara zionis Israel.










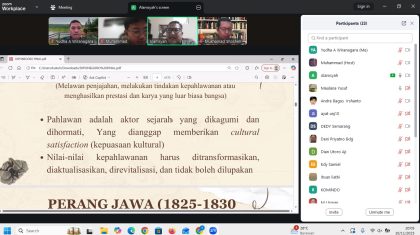


















Komentar